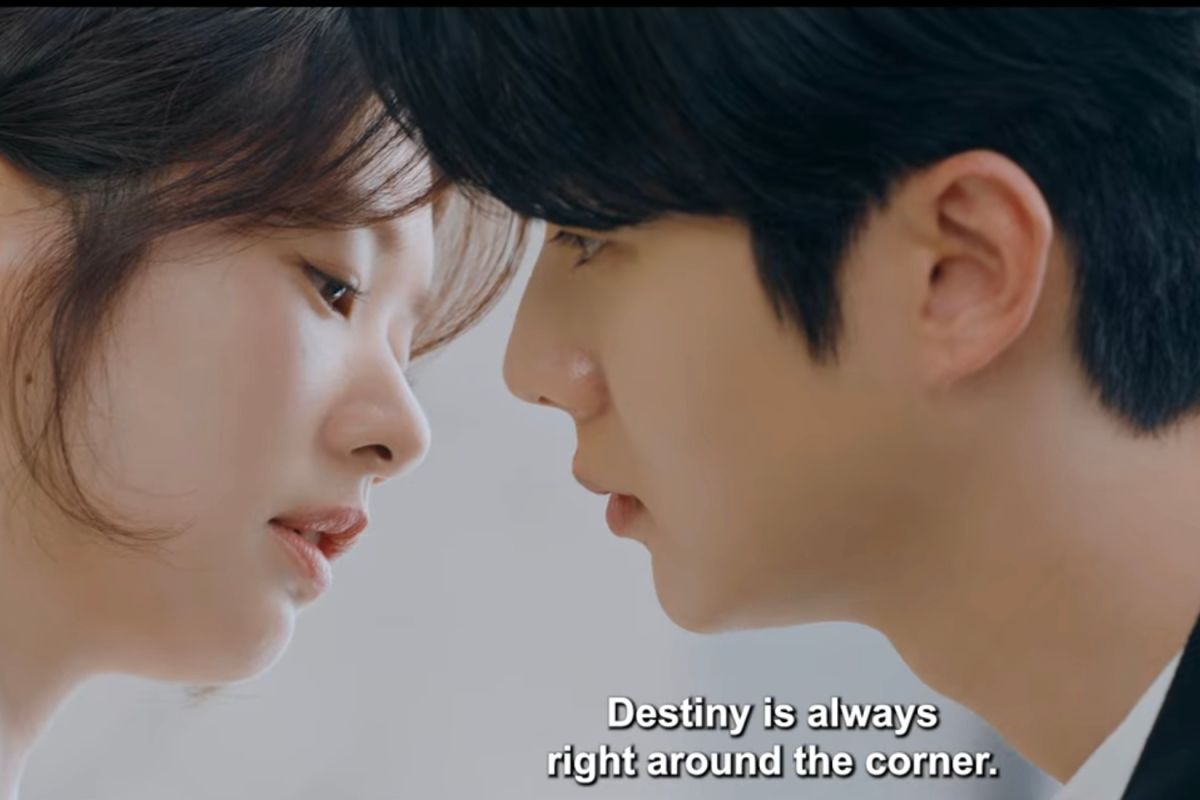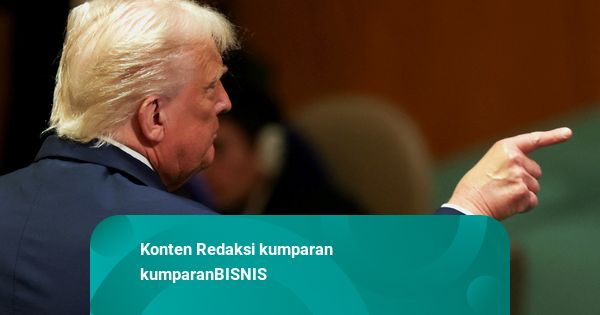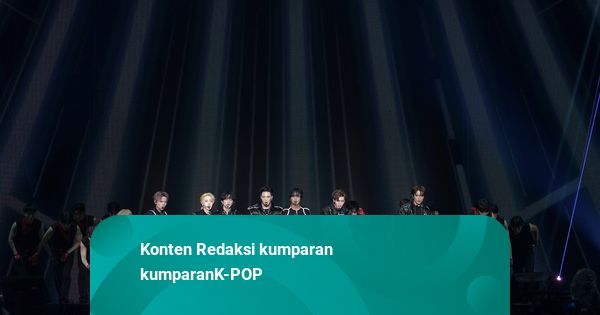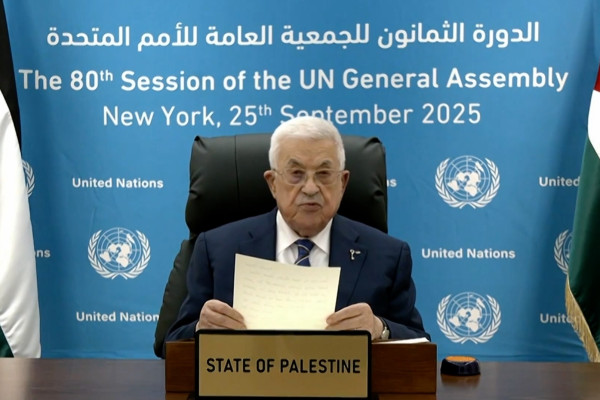Sarasehan bertajuk "Diskusi Seni: Interpretasi, Refleksi, Transformasi Tari Cangget dalam Praktik Penciptaan Seniman dan Komunitas Tari di Lampung Utara" pada 21 September 2025 lalu menyisakan ingatan yang menarik untuk direnungkan kembali: memperbincangkan tari sebagai laku seni.
Sesungguhnya, perdebatan tentang hakikat tari telah lama hadir. Apakah tari mesti dipahami sebagai laku, yakni gerak tubuh yang dijalani dan dihidupi; atau sebagai teori, yaitu kerangka konseptual yang menafsirkan dan menjelaskan tari? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tetapi implikasinya sangat luas: ia menyentuh cara kita memandang seni, tubuh, bahkan pengetahuan itu sendiri.
Di satu sisi, bagi para praktisi, tari pada dasarnya adalah laku. Tari hidup dalam tubuh penari, bukan catatan di atas kertas atau rangkaian kata yang dilisankan. Namun, pada sisi lain, bagi para teoretikus—tanpa kerangka konseptual—tari berisiko hilang bersama para pelakunya.
Pada situasi ataupun wilayah semacam itulah perguruan tinggi perlu memainkan perannya, dengan menegaskan pada pemahaman bahwa tari adalah pengetahuan ganda: laku sekaligus teori. Dalam hal ini, Filsuf Maurice Merleau-Ponty mengatakan bahwa tubuh bukan sekadar objek biologis, melainkan media kita untuk mengalami dunia "the body is our general medium for having a world" (Merleau-Ponty, 1962: 129). Dengan demikian, penari tidak hanya "menjalankan" gerakan, tetapi menghadirkan dunia melalui tubuhnya. Di sinilah tari menjadi pengalaman yang tak sepenuhnya bisa dituliskan atau diwicarakan: ia adalah embodied knowledge, sebuah pengetahuan yang hanya bisa dimengerti jika dilaksanakan.
Teori memungkinkan tari ditafsirkan, diarsipkan, dan diwariskan lintas generasi. Ia membuka jalan bagi kritik sosial, analisis budaya, bahkan refleksi filosofis. Tari, dalam pandangan ini, bukan hanya ekspresi tubuh, melainkan juga teks budaya yang sarat makna: tentang identitas, gender, kekuasaan, hingga politik. Tari tak ubahnya sebuah teks yang mungkin dibaca, diinterpretasi, dan dianalisis. Irama gerak tubuh penari adalah "tanda" dalam sistem representasi; artinya identitas, gaya, kekuasaan, dan sejarah semua tecermin di dalamnya.
Seolah hendak menegaskan, Susan Leigh Foster menyebut bahwa hakikat tarian yakni "to show the body's capacity to both speak and be spoken through in many different languages" (Foster, 1986: 188). Tubuh dalam tari tidak pernah netral; ia sekaligus menjadi subjek yang aktif dan objek yang pasif dalam produksi makna. Tubuh dapat "berbicara" melalui gerak, gestur, dan ekspresi, sehingga menghadirkan bahasa yang tak selalu hadir dalam kata-kata, tetapi pada saat yang sama tubuh juga "dibicarakan" oleh beragam wacana sosial, budaya, politik, dan historis yang melekat padanya.
Dengan demikian, tubuh penari berfungsi sebagai teks ganda: ia mengartikulasikan pengalaman dan identitas, sekaligus menjadi media tempat norma dan ideologi bekerja. Dalam kerangka ini, tari bukan hanya pertunjukan estetik, melainkan ruang di mana tubuh bernegosiasi dengan banyak bahasa dan makna, sehingga teori menjadi penting agar lapisan-lapisan simbolik tersebut dapat ditafsirkan, diarsipkan, dan diwariskan lintas generasi.
Pada akhirnya, tari hendaknya dipahami sebagai pengetahuan ganda: laku yang dihidupi tubuh sekaligus teori yang menafsirkannya. Perguruan tinggi dalam hal ini berperan penting bukan hanya sebagai ruang pelestarian praktik tari, melainkan juga sebagai laboratorium intelektual yang menafsirkan, mengarsipkan, dan mengembangkan wacana tentang tubuh serta makna yang dikandungnya. Melalui sinergi antara praktik dan teori, perguruan tinggi dapat memastikan bahwa tari tidak berhenti pada panggung pertunjukan semata, melainkan menjadi pengetahuan yang hidup, kritis, dan relevan lintas generasi.

 1 month ago
43
1 month ago
43

,x_140,y_26/01kax7hxp9gssg76ng2npxjbe4.jpg)
,x_140,y_26/01kax76yr9hjr5fbw2c24n1n5g.jpg)
,x_140,y_26/01kax6rwg34neek8ya75cbpsz1.jpg)