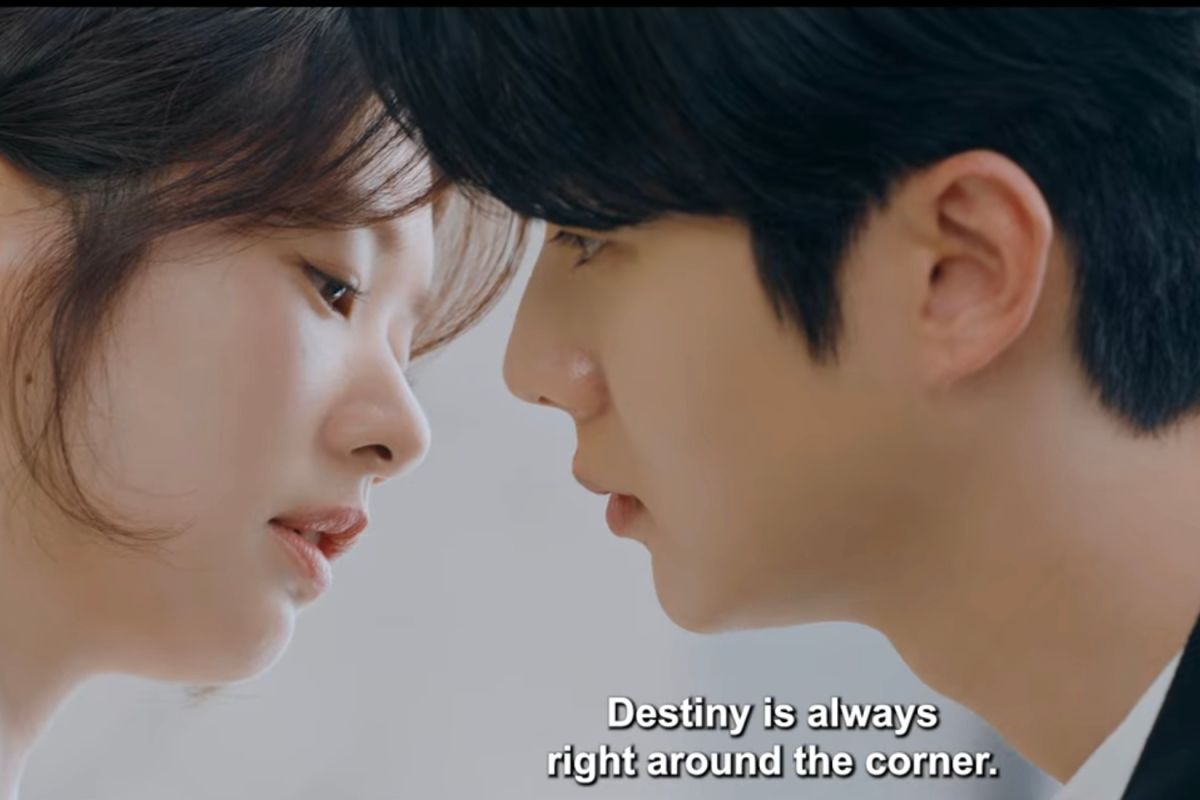Kita terbiasa melihatnya. Gunung-gunung baru yang lahir bukan dari aktivitas tektonik, melainkan dari kerakusan dan kelalaian kita, menjulang busuk di Bantar Gebang, di Suwung, di Piyungan.
Lautan kita, yang dulu jadi sumber kidung dan puisi, kini menjadi sup plastik raksasa yang mencekik biota. Lalu, dengan serempak, telunjuk kita mengarah ke satu target empuk: “masyarakat”. Katanya, kita pemalas. Katanya, kita tidak punya kesadaran.
Selama puluhan tahun, narasi ini dijejalkan ke tenggorokan kita. Kita adalah terdakwa utama dalam drama ekologis yang kita ciptakan sendiri.
Izinkan saya mengatakan ini dengan lantang: narasi itu adalah kebohongan besar. Sebuah pengalihan isu yang nyaman untuk menutupi borok yang sesungguhnya. Akar masalah sampah di negeri ini bukanlah kemalasan warganya. Akarnya adalah ketidakadilan yang dipelihara oleh negara.
Negara Hadir untuk Listrik, Absen untuk Sampah
Mari kita bicara angka, agar tidak dituduh sekadar berteriak. Rasio elektrifikasi Indonesia sudah gagah perkasa mendekati 100%. Negara, dengan segala kekuatannya, berhasil menarik kabel, mendirikan tiang, dan menerangi rumah-rumah di puncak gunung hingga pesisir terpencil. Sebuah pencapaian yang patut kita apresiasi.
Sekarang, mari kita lihat angka satunya lagi: rasio pelayanan sampah nasional. Angka ini, dengan memalukan, mandek di kisaran 39–40%. Tidak bergeser signifikan selama bertahun-tahun.
Cerna ini perlahan: negara sanggup mengantarkan elektron ke hampir 280 juta jiwa, tetapi gagal mengangkut sisa makanan dan plastik dari 60% warganya.
Bagaimana mungkin kita menuntut seorang ibu di dusun terpencil untuk memilah sampah organiknya, jika truk sampah bahkan tidak pernah menyentuh jalan desanya? Bagaimana kita bisa menyalahkan seorang pedagang di pasar kumuh yang membuang sampahnya ke sungai, jika tidak pernah ada satu pun tempat sampah atau layanan pengangkutan yang disediakan untuknya?
Kita menyalahkan korban. Kita menghakimi mereka yang tidak punya pilihan. Ini bukan lagi soal teknis pengelolaan sampah. Ini adalah soal keadilan sosial yang terang-terangan diinjak-injak.
Bukan masyarakat yang lalai. Negara yang abai.
WTE: Ilusi Megah di Tengah Ketimpangan
Pemerintah kini datang dengan solusi berkilauan: Waste to Energy (WTE). Proyek raksasa seperti Danantara digadang-gadang akan mengubah sampah menjadi listrik. Investasi triliunan rupiah digelontorkan. Para pejabat bertepuk tangan, merasa telah menemukan peluru perak untuk monster sampah.
Jangan salah, saya tidak anti-teknologi. Namun, WTE dalam konteks ketidakadilan saat ini adalah seperti membangun penthouse mewah di atas fondasi gubuk yang reyot.
WTE hanya akan melayani kota-kota besar yang mampu menyetor ribuan ton sampah setiap hari. Proyek ini akan menyedot anggaran dan perhatian, sementara 60% wilayah Indonesia yang lain tetap dibiarkan menjadi yatim piatu peradaban sampah. Desa-desa akan terus membakar plastiknya di pekarangan, dan sungai-sungai di pelosok akan tetap menjadi tempat sampah terpanjang di dunia.
Pemerintah pusat terobsesi dengan proyek mercusuar, solusi instan yang fotogenik. Mereka lupa bahwa pekerjaan paling fundamental—dan paling tidak seksi—adalah memperluas jangkauan pelayanan sampah hingga ke gang-gang sempit dan dusun-dusun terpencil. Pemerintah daerah pun latah, berlomba-lomba mengajukan proposal WTE tanpa pernah serius bertanya: sudahkah seluruh wargaku terlayani?

 1 month ago
35
1 month ago
35