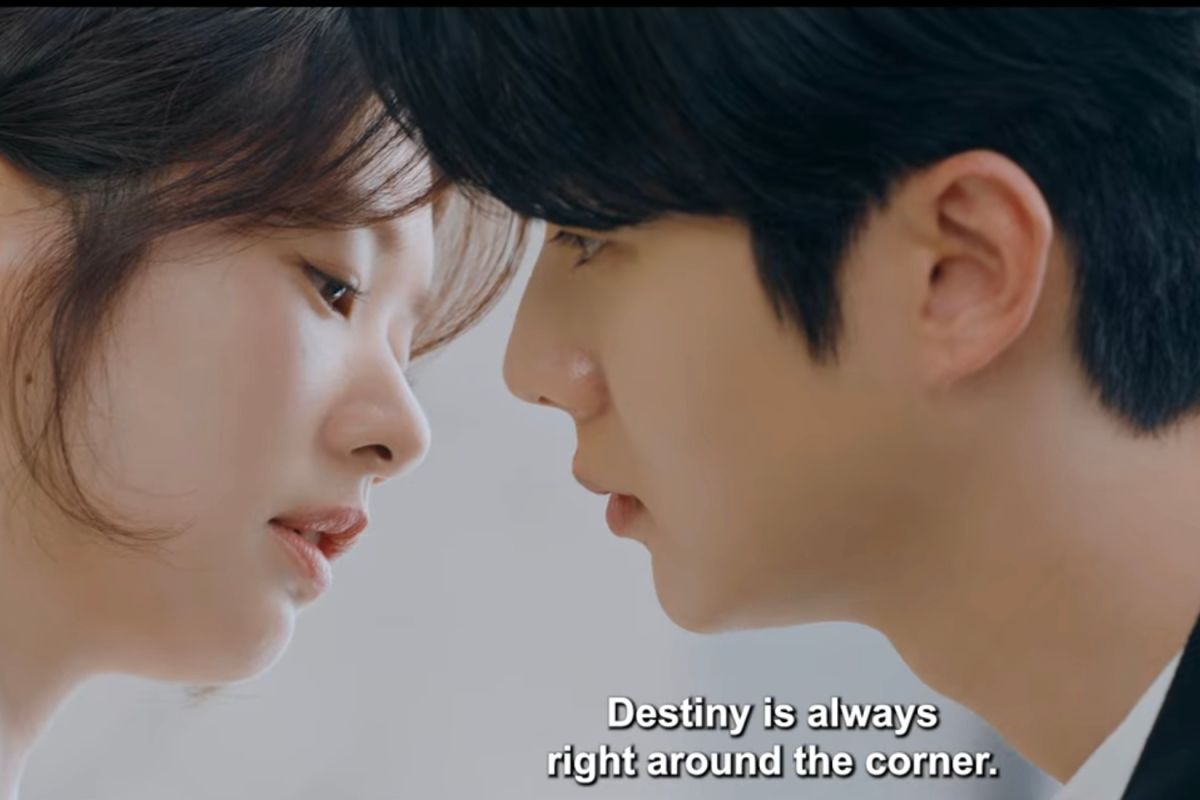Ketika Mantan Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Kereta Cepat Jakarta—Bandung (Whoosh) bukan proyek untuk mencari laba, melainkan investasi sosial, pernyataan itu mengandung pesan politik dan ekonomi yang kuat. Ia ingin menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur besar bukan sekadar hitung-hitungan keuntungan finansial, melainkan soal manfaat sosial jangka panjang.
Menurutnya, transportasi massal seperti Whoosh harus dilihat sebagai sarana publik untuk mengurangi kemacetan, menekan polusi, serta menghemat waktu dan energi. Dalam logika itu, negara memang tak perlu menuntut laba langsung, sebab manfaat ekonominya akan muncul dalam bentuk efisiensi nasional.
Namun, di sisi lain hal itu mengundang perdebatan. Investasi sosial, menurut sejumlah pengamat, justru lebih menyerupai layanan premium yang dinikmati kalangan menengah—atas. “Whoosh bukan layanan sosial, yang menikmati orang kaya,” demikian salah satu tajuk media yang ramai diperbincangkan.
Di sinilah ketegangan muncul: antara narasi ideal pemerintah dan realitas sosial di lapangan. Apakah proyek yang menelan biaya ratusan triliun rupiah itu benar-benar menjadi investasi yang inklusif, atau justru simbol kemajuan yang hanya bisa diakses sebagian kecil masyarakat?
Investasi Sosial yang Belum Inklusif
Dalam teori ekonomi publik, investasi sosial berarti investasi yang hasilnya bukan secara langsung berupa keuntungan uang, melainkan manfaat sosial yang lebih luas: pengurangan kemiskinan, peningkatan mobilitas sosial, dan efisiensi ekonomi. Namun, untuk bisa disebut demikian, manfaatnya harus dirasakan oleh publik luas—bukan hanya oleh mereka yang mampu membayar lebih.
Di titik inilah, klaim itu mulai dipertanyakan. Tarif Whoosh relatif tinggi dibanding moda transportasi lain. Rutenya terbatas, belum terintegrasi penuh dengan jaringan transportasi perkotaan. Akibatnya, bagi masyarakat pekerja menengah ke bawah, moda supercepat ini belum menjadi pilihan rasional.
Jokowi memang benar bahwa kemacetan di Jakarta—Bandung menimbulkan kerugian besar, bahkan mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Namun, pertanyaannya: Sejauh mana kereta cepat berkontribusi nyata mengurangi beban itu jika penumpangnya hanya pada golongan tertentu?
Kalangan kritikus menilai proyek ini terlalu cepat dideklarasikan sebagai layanan publik, padahal secara faktual masih beroperasi layaknya layanan komersial. Bahkan, ada kekhawatiran bahwa beban utang luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek tersebut akan menjadi tanggungan fiskal jangka panjang.
Jika manfaat sosial tidak sebanding dengan beban ekonomi, yang disebut investasi sosial berisiko berubah menjadi liabilitas sosial—beban kolektif yang pembayarannya diambil dari pajak publik dan itu sudah terjadi melalui penyertaan modal negara.
Lebih jauh, kehadirannya sejauh ini belum tampak mendorong pemerataan ekonomi di sepanjang jalurnya. Kawasan sekitar stasiun belum benar-benar berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi rakyat, melainkan cenderung diarahkan ke proyek properti besar yang bernilai tinggi. Alih-alih menjadi jembatan pembangunan inklusif, Whoosh berpotensi memperlebar jarak antara pusat dan pinggiran.
Dari SBY ke Jokowi: Pergeseran Paradigma Pembangunan
Untuk memahami mengapa proyek ini muncul dan menjadi simbol kebanggaan nasional, kita perlu melihat pergeseran orientasi pembangunan dari satu dekade ke dekade berikutnya.
Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan ekonomi berpusat pada stabilitas makro dan pemerataan berbasis program sosial. Infrastruktur tetap dibangun, tetapi dengan pendekatan kehati-hatian fiskal. Fokus utamanya adalah pro-growth, pro-job, dan pro-poor—pertumbuhan disertai pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

 2 weeks ago
9
2 weeks ago
9