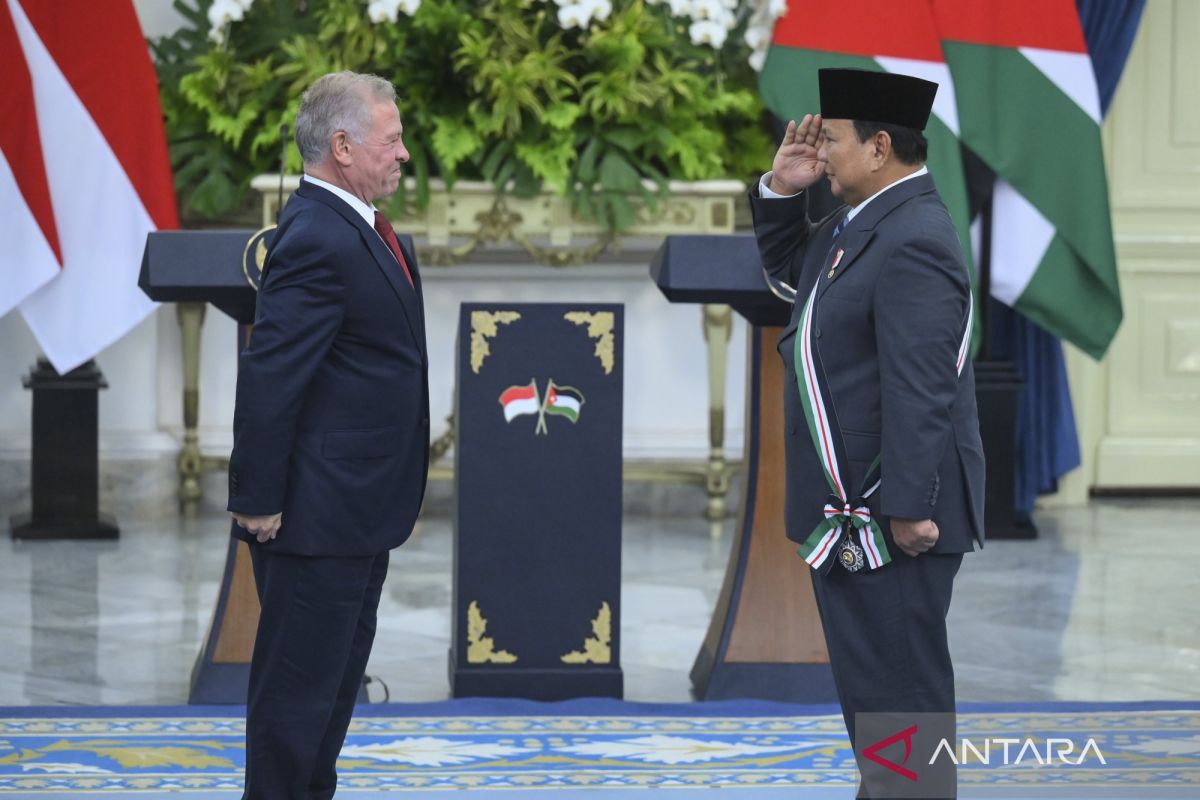Dalam cerita-cerita perang yang disampaikan di sekolah, diberitakan media, atau diabadikan film-film Hollywood, selalu ada sosok pahlawan gagah yang berdiri di garis depan: tentara laki-laki. Mereka yang memegang senjata, mengambil risiko, dan menyelamatkan negara.
Tetapi ada satu tokoh yang jarang sekali mendapat ruang dalam narasi besar ini perempuan. Padahal ketika bom meledak, ketika anak-anak berlari mencari perlindungan, ketika tubuh-tubuh terluka menunggu pertolongan, perempuanlah yang menjadi penopang kehidupan. Namun sayangnya, kontribusi mereka sering hanya dicatat sebagai pelengkap, bukan inti cerita.
Cynthia Enloe, tokoh sentral dalam teori feminisme internasional, sudah lama menggugat narasi tunggal ini. Di bukunya Bananas, Beaches and Bases (1989), ia melontarkan pertanyaan sederhana tapi dalam: “Where are the women in war?” Pertanyaan yang terdengar simpel, tapi memporak-porandakan cara kita melihat perang dan politik global. Enloe menunjukkan bahwa hubungan internasional dibangun dari kacamata maskulinitas keras, agresif, penuh kompetisi, seolah-olah dunia hanya digerakkan oleh laki-laki dan logika perang.
Militerisasi dan Maskulinitas: Dunia yang Didesain untuk Laki-Laki
Dalam budaya politik global, perang selalu diidentikkan dengan maskulinitas. Nilai seperti keberanian, kekuatan fisik, dan pengorbanan dijadikan standar moral tertinggi. Semua itu dilekatkan pada tubuh laki-laki. Mereka adalah pahlawan, pembela negara, simbol kejantanan nasional.
Sementara perempuan? Mereka dijadikan simbol emosional: ibu bangsa, penjaga rumah, perawat korban. Mereka boleh muncul dalam momen seremonial mengantar tentara pergi, menangis di pemakaman, atau menjadi ikon kesedihan tapi bukan aktor yang menentukan arah sejarah.
Ketika strategi disusun di meja militer, suara perempuan tidak diminta. Ketika perdamaian dirumuskan, mereka jarang diberi kursi. Dalam banyak konflik, perempuan sering digambarkan sebagai pihak yang harus dilindungi, bukan pihak yang memiliki kapasitas pengambilan keputusan.
Padahal kenyataannya jauh berbeda.
Perempuan yang Bertahan, Mengatur, dan Memastikan Hidup Terus Berjalan
Dalam situasi perang, perempuan bukan hanya merawat, tetapi mengelola kehidupan dari nol. Mereka mengatur dapur umum, memindahkan keluarga ke daerah aman, menjaga anak-anak tetap tenang, membangun jaringan solidaritas di tengah kehancuran, bahkan menjadi tulang punggung ekonomi ketika para laki-laki pergi ke medan perang.
Namun di banyak wilayah konflik, laporan UN Women (2023) menunjukkan bahwa perempuan di kamp pengungsian jarang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan komunitas. Mereka dianggap penerima bantuan, bukan pemikir atau perancang solusi. Seolah-olah kemampuan perempuan hanya berhenti pada kerja-kerja perawatan, padahal merekalah yang paling memahami kebutuhan komunitas.
Sosiolog feminis Sylvia Walby menyebut kondisi ini sebagai “reproduksi patriarki modern.” Ini bukan patriarki yang keras dan gamblang, tapi patriarki yang lembut, halus, tapi mengukuhkan ketimpangan secara struktural. Perempuan ditempatkan dalam posisi aman tapi sekaligus disingkirkan dari ruang strategis.
Pendidikan: Ruang yang Lama Dikunci untuk Perempuan
Sebelum perempuan dapat duduk di meja perdamaian, mereka terlebih dahulu harus melawan pengucilan dari dunia pendidikan. Selama ratusan tahun, perempuan dilarang belajar tentang politik, strategi militer, atau diplomasi. Penghalangan ini bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena sistem takut kehilangan monopoli pengetahuan yang memihak laki-laki.
Bell hooks, pemikir feminis terkemuka, mengatakan bahwa pendidikan adalah bentuk feminist resistance senjata perlawanan yang memberikan perempuan ruang untuk berbicara, menulis, dan menentukan narasi sendiri. Ketika perempuan masuk ke dunia ilmu pengetahuan, mereka sedang mengguncang struktur lama yang selama ini mengabaikan mereka.

 1 month ago
38
1 month ago
38