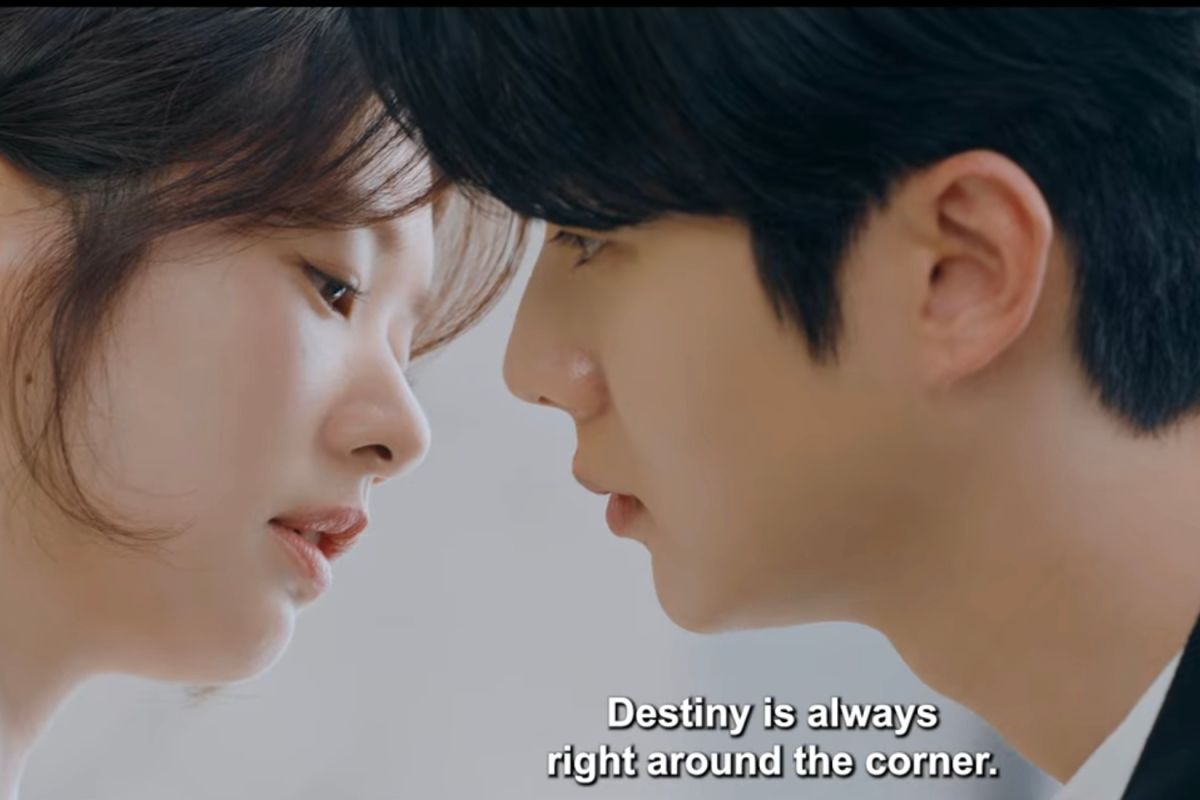Polemik mengenai Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak pernah sepenuhnya soal teknologi atau kebanggaan nasional.
Ia selalu membawa konsekuensi sosial, ekonomi, dan politik yang berkaitan dengan pertanyaan mendasar: siapa yang membayar dan siapa yang menikmati manfaatnya?
Dalam perspektif sosiologis, terutama perspektif kelas, proyek ini memperlihatkan bahwa distribusi risiko dan manfaat pembangunan tidak pernah netral. Ia mengikuti struktur kekuasaan, kepentingan negara, dan posisi tawar antarkelompok sosial.
Proyek KCJB menelan biaya sekitar 120 hingga 125 triliun rupiah, angka yang membengkak dari perencanaan awal. Pembengkakan biaya (cost overrun) ini kemudian memaksa penyesuaian struktur pembiayaan, termasuk penambahan porsi utang yang ditanggung oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai pemimpin konsorsium.
Padahal KAI bukan hanya mengelola kereta cepat, tetapi juga layanan transportasi publik sehari-hari yang digunakan jutaan orang, seperti KRL Jabodetabek, kereta perintis, dan kereta kelas ekonomi.
Ketika beban pembayaran bunga sekitar dua triliun rupiah per tahun harus dimasukkan dalam neraca keuangan KAI, maka risiko penyesuaian tarif atau pengurangan subsidi sangat mungkin terjadi.
Di titik ini, beban ekonomi proyek yang sejak awal disebut sebagai kerja sama bisnis ke bisnis (B2B) mulai perlahan berpindah ke ruang sosial, yaitu ke masyarakat yang menjadi pengguna layanan transportasi lain.
Dengan kata lain, kelas pekerja yang belum tentu pernah naik kereta cepat pun bisa ikut “membayar” proyek ini melalui kenaikan tarif transportasi massal atau pengurangan layanan publik.
Inilah pola yang dikenal dalam kajian sosiologi pembangunan sebagai redistribusi beban ke bawah, ketika proyek yang berorientasi prestise dan pertumbuhan ekonomi elitis menimbulkan dampak struktural bagi kelompok yang tidak memiliki kendali terhadap keputusan kebijakan.
Mobilitas sebagai Cermin Ketimpangan Kelas
Untuk memahami siapa yang benar-benar memanfaatkan kereta cepat, kita harus melihat data penggunaan dan pola perjalanan. Sejak beroperasi, KCJB mencatat lonjakan penumpang terutama pada akhir pekan dan musim liburan.
Pada hari kerja, jumlah penumpang jauh lebih rendah. Selain itu, okupansi tertinggi sering terjadi ketika terdapat diskon tarif, bukan pada tarif normal. Kondisi ini menunjukkan bahwa kereta cepat lebih banyak digunakan sebagai moda perjalanan rekreasi dan gaya hidup, bukan sebagai moda mobilitas harian yang mendukung aktivitas ekonomi pekerja.
Gambaran ini diperkuat oleh pengamatan lapangan: banyak penumpang membawa koper besar atau perlengkapan wisata. Sangat jarang terlihat komuter yang memakai seragam kantor atau membawa tas kerja.
Pada saat yang sama, pekerja harian yang tinggal di wilayah sekitar Jakarta dan Bandung tetap mengandalkan kereta biasa, KRL, angkot, dan bus sebagai moda transportasi utama. Hal ini memperlihatkan bahwa kelas sosial menentukan akses mobilitas bahkan ketika infrastruktur baru telah dibangun.
Kereta cepat juga menghadapi masalah keterhubungan ruang. Stasiun-stasiunnya tidak berada di pusat kota, melainkan di Padalarang dan Tegalluar. Pengguna harus menggunakan moda lanjutan untuk mencapai pusat Bandung, yang menambah biaya, waktu, dan ketidakpastian perjalanan.
Bagi pekerja harian, mobilitas bukan hanya soal kecepatan, tetapi soal kepastian dan keterjangkauan. Jika satu moda transportasi tidak memberikan keduanya, maka ia hanya akan menjadi alternatif bagi mereka yang memiliki kelonggaran finansial dan waktu.
Dalam ...

 2 weeks ago
26
2 weeks ago
26