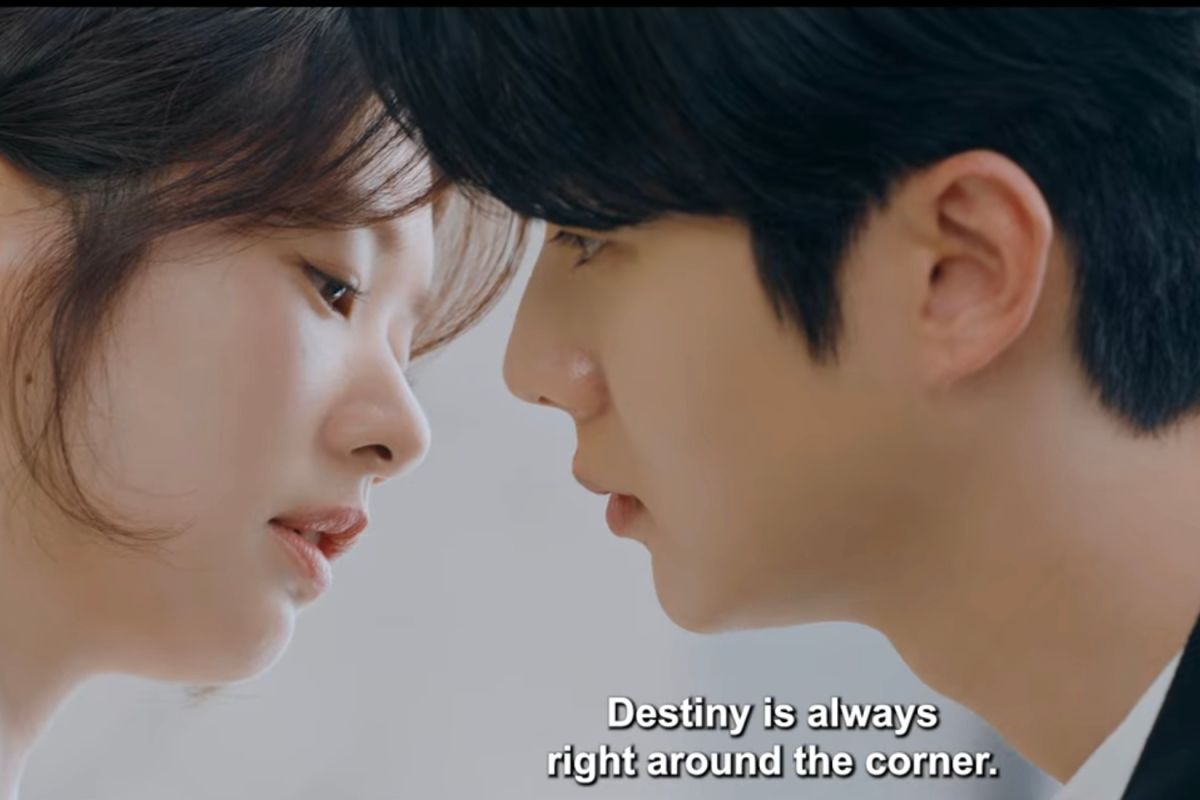Ujian skripsi dulunya dikenal sebagai momen sakral dalam perjalanan akademik seorang mahasiswa. Ujian skripsi adalah gerbang terakhir menuju gelar sarjana, sekaligus ruang pengakuan atas kemampuan intelektual yang ditempa selama bertahun-tahun. Namun, belakangan ini, kesakralan itu seakan memudar. Ujian skripsi kini kerap tampil bukan sebagai panggung intelektual, melainkan sebagai ajang selebrasi, bahkan lebih jauh telah menjadi “panggung pencitraan”.
Fenomena ini semakin terasa di era media sosial. Setiap periode sidang skripsi, lini masa kita mendadak dipenuhi dengan unggahan foto dan video mahasiswa bersama keluarga dan sahabat. Tidak jarang, nuansa yang tampak justru lebih mirip pesta pernikahan ketimbang ujian akademik. Selempang dengan nama lengkap dan gelar yang bahkan belum sah, buket bunga yang harganya tak main-main, hingga baliho mini yang menyerupai ucapan selamat untuk pejabat negara.
Pertanyaan mendasar, kapan sebenarnya gelar itu resmi disandang? Jawabannya jelas, setelah yudisium, ketika surat keputusan disahkan oleh pejabat berwenang di kampus. Maka, mengenakan selempang bergelar sebelum momen itu sejatinya adalah bentuk manipulasi simbolik. Sebuah gelar yang belum sah ditampilkan seakan sudah final.
Ada paradoks menarik dalam tren ini. Di luar ruang sidang, kita melihat euforia berlebihan, sementara di dalam justru sering terdengar keheningan. Tidak sedikit mahasiswa yang tampil percaya diri di depan kamera, tetapi gagap ketika ditanya mengenai substansi skripsinya. Mereka bingung menjelaskan alasan pemilihan metode penelitian, bahkan tidak mampu menguraikan kerangka teori yang digunakan.
Di sinilah letak keprihatinannya. Ujian skripsi yang seharusnya menguji ketajaman berpikir, justru berubah menjadi formalitas administratif. Sementara itu, selebrasi pasca-sidang berkembang menjadi sebuah "ritual wajib", seakan kelulusan tanpa pesta dianggap kurang sah.
Apakah selebrasi itu salah? Tentu tidak. Perayaan adalah bagian dari budaya manusia. Ia menjadi ekspresi rasa syukur setelah melalui proses panjang dan penuh tantangan. Namun, persoalannya terletak pada kadar dan orientasi. Ketika selebrasi lebih megah daripada kualitas akademik, kita patut bertanya, apa sebenarnya makna menjadi seorang sarjana?
Fenomena ini tidak berhenti pada individu, melainkan merembes ke masyarakat luas. Sarjana dipersepsikan bukan lagi sebagai sosok yang berilmu dan mampu memberi kontribusi, melainkan sekadar gelar yang bisa dipamerkan. Gelar menjadi komoditas simbolik, bukan tanda kompetensi.
Lebih jauh, budaya selebrasi ini berpotensi mendorong hedonisme akademik. Mahasiswa terdorong untuk mengejar pengakuan sosial lewat kemewahan perayaan, alih-alih menekankan substansi intelektual. Bagi sebagian keluarga, muncul pula beban sosial—merasa harus mengikuti tren selebrasi agar tidak dianggap kurang mampu atau kurang berprestasi.
Ironisnya, di tengah gegap gempita ucapan selamat di media sosial, masih ada lulusan yang kesulitan menjawab wawancara kerja sederhana. Ada pula yang tidak mampu menulis laporan portofolio (curriculum vitae) dengan baik, meski baru saja melewati proses penelitian. Ketimpangan ini mencerminkan adanya jurang antara gelar formal dan kompetensi riil.
Dalam tradisi akademik, sarjana bukan sekadar status sosial, melainkan amanah. Ia adalah simbol bahwa pemiliknya telah ditempa dalam disiplin ilmu tertentu, mampu berpikir kritis, dan memiliki tanggung jawab moral untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Jika gelar hanya dipandang sebagai ornamen untuk foto dan perayaan, maka kita tengah mengikis makna luhur pendidikan tinggi. Kampus yang semestinya menjadi kawah candradimuka intelektual, berisiko berubah menjadi panggung seremonial belaka.
Di sinilah peran dosen, pengelola kampus, bahkan keluarga menjadi penting. Kampus perlu mengembalikan marwah ujian skripsi sebagai ruang dialog akademik. Bukan sekadar menilai hasil tulisan, tetapi juga menguji proses berpikir mahasiswa. Ujian skripsi harus menjadi arena di mana mahasiswa diuji kematangan intelektualnya, bukan hanya kemampuan bertahan dari gugup.
Sementara itu, keluarga dan masyarakat juga perlu menata ulang cara pandang. Perayaan kelulusan boleh saja, tetapi hendaknya proporsional. Tidak perlu terjebak pada glamoritas yang justru mengaburkan makna perjuangan akademik itu sendiri.
Mahasiswa, dengan segala kreativitasnya, tentu sah-sah saja merayakan momen ...

 3 weeks ago
29
3 weeks ago
29