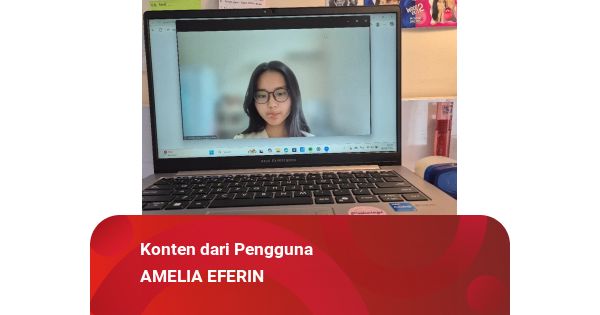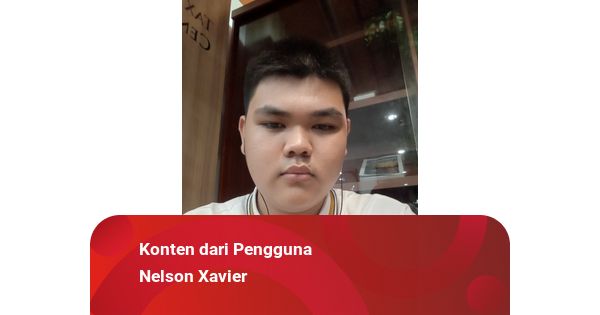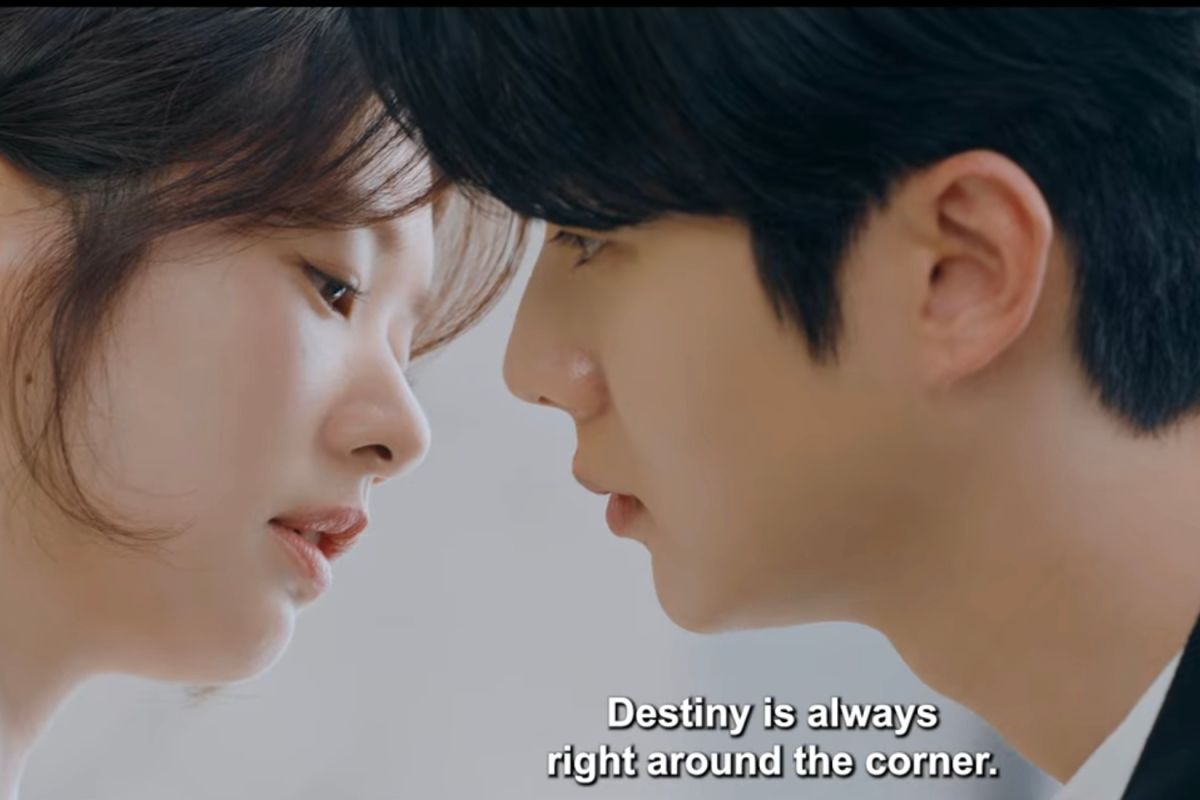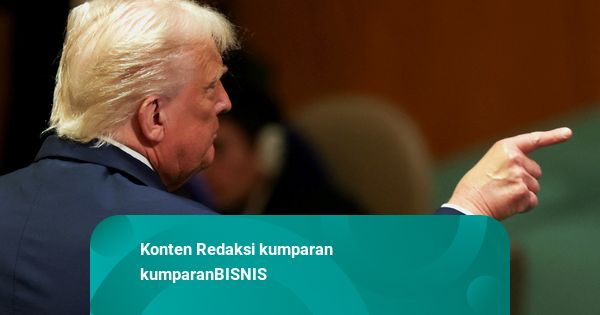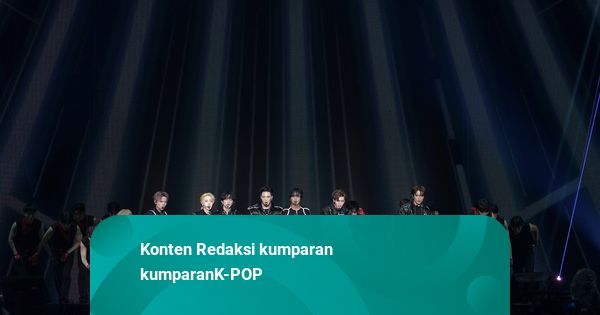Harga udang tidak sekadar angka di pasar komoditas, ia adalah ‘kompas’ yang menentukan arah strategi produksi, manajemen tambak, hingga pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di sektor akuakultur. Ketika harga udang naik, gairah produksi petambak melonjak. Padat tebar diperbesar, pakan dipacu, siklus produksi dipercepat.
Namun bersamaan dengan euforia itu, ancaman penyakit udang pun meningkat drastis. Sebaliknya, ketika harga turun, biaya operasional ditekan, dan ironisnya, yang sering dipangkas pertama kali adalah anggaran biosekuriti dan pengawasan teknis, dua aspek yang justru paling menentukan keberlangsungan produksi.
Fluktuasi harga ini bukan sekadar dinamika pasar domestik. Menurut Food and Agriculture Organization (FAO, 2023), dalam lima tahun terakhir (2019–2023) harga udang global mengalami fluktuasi tajam hingga 35–45%. Ketergantungan Indonesia terhadap pasar ekspor, terutama Amerika Serikat, Jepang, dan Tiongkok, menjadikan industri ini sangat sensitif terhadap dinamika ekonomi dan kebijakan luar negeri negara tujuan ekspor.
Ketika harga ekspor naik, banyak tambak memperluas tebaran dan memperpendek siklus pemeliharaan untuk mengejar momentum harga. Namun praktik ini sering kali diikuti peningkatan stres lingkungan, penumpukan limbah organik, dan munculnya penyakit pada udang.
Tekanan Ekspor dan Hambatan Pasar Global
Selain tekanan fluktuasi harga, ada faktor penting lain yang jarang diulas di tingkat petambak: hambatan ekspor non-tarif. Dalam beberapa bulan terakhir, industri perudangan Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menembus pasar Amerika Serikat dan Jepang. Salah satunya terkait isu kontaminasi radioaktif pada produk perikanan dan udang beku yang masuk ke Jepang, terutama setelah meningkatnya pengawasan ketat pasca pelepasan air olahan dari PLTN Fukushima (FAO & WHO, 2023). Jepang memperketat standar Maximum Residue Limits (MRL) dan melakukan uji acak terhadap produk perikanan, termasuk udang.
Di sisi lain, pasar AS juga semakin memperketat standar keamanan pangan, terutama terkait cemaran mikroba dan residu bahan kimia. Menurut data United States Food and Drug Administration (FDA, 2024), beberapa pengiriman udang dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia, pernah ditolak karena tidak memenuhi standar keamanan. Kondisi ini menimbulkan tekanan ganda: petambak harus meningkatkan volume dan kualitas produksi untuk tetap kompetitif, tetapi pada saat yang sama harus menghadapi risiko penyakit dan biaya operasional yang tinggi.
Ketergantungan yang besar pada ekspor membuat sektor budidaya udang Indonesia sangat rentan. Ketika ada hambatan pasar di luar negeri, harga domestik tertekan dan mendorong efisiensi ekstrem di tingkat tambak. Dan sering kali, efisiensi itu dilakukan dengan cara yang salah: mengurangi pengawasan teknis dan menurunkan standar biosekuriti.
Penyakit EHP dan Vibriosis: 'Pembunuh Senyap' Produksi
Dalam kondisi tekanan pasar yang tinggi, penyakit menjadi faktor penentu produktivitas. Jika White Spot Syndrome Virus (WSSV) atau Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) dikenal sebagai 'pembunuh cepat' di tambak, maka Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) dan Vibriosis adalah 'pembunuh senyap' yang menghancurkan produktivitas secara perlahan.
EHP menyebabkan pertumbuhan udang lambat dan ukuran panen tidak seragam. Penelitian oleh Tangprasittipap et al. (2013) menunjukkan EHP dapat menurunkan pertumbuhan udang hingga 30–40% dan menyebabkan size variation yang tinggi pada panen. Hal ini berdampak langsung pada nilai jual dan efisiensi panen, terutama saat harga ekspor sedang turun. Sementara itu, vibriosis, yang disebabkan oleh bakteri Vibrio spp., memperburuk kondisi kesehatan udang terutama pada fase pertumbuhan tengah hingga akhir, sering menyebabkan mortalitas bertahap (chronic mortality).

 1 month ago
15
1 month ago
15