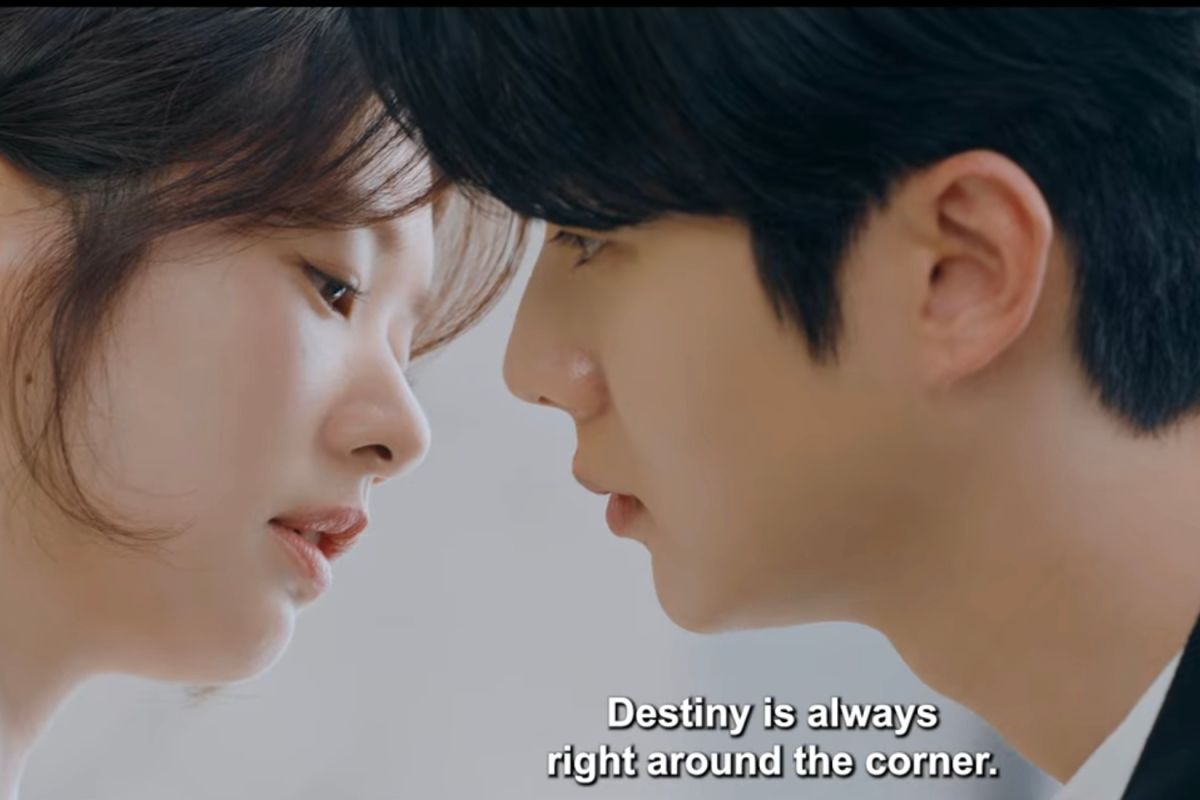Kita semua pernah tinggal di “rumah” kenangan—tempat segala hal terasa akrab, meski sudah tak nyaman. Dulu, rumah itu penuh romansa, gelak tawa, serta mimpi-mimpi dan rencana. Namun sekarang, yang tersisa hanyalah gema langkah kita sendiri. Fenomena gagal move on bukan sekadar cinta yang belum padam, melainkan tentang keengganan untuk meninggalkan tempat yang pernah membuat kita merasa hidup. Padahal, rumah itu—yang dulu terasa hangat—kini sudah bocor dari segala sisi.
Ada perasaan sentimental yang aneh: kita tahu sudah waktunya keluar, tapi tetap duduk di ruang tamu kenangan, menatap foto lama, berharap sesuatu yang tak akan kembali. Mungkin, sebenarnya kita bukan mencintai orangnya, melainkan perasaan yang dulu pernah membuat kita terasa jauh lebih hidup.
Antara Otak yang Rasional dan Hati yang "Membandel"
Menurut penelitian Denise R. Beike dan Elizabeth T. Wirth-Beaumont (2005), seseorang baru benar-benar bisa merasa closure atau penutupan emosional ketika intensitas emosi di balik kenangan sudah menurun. Semakin kuat perasaan yang tertinggal, semakin lama kita “terjebak” di sana.
Saya merasa konsep ini menjelaskan mengapa banyak orang yang tampak sudah “melupakan” secara logika masih terikat secara emosi. Otak tahu hubungan itu sudah selesai, tapi hati belum menemukan titik tenang. Dan sering kali, yang kita rindukan bukan orangnya, melainkan perasaan dicintai ketika bersama dia. Kita menolak kenyataan bukan karena tidak paham, melainkan masih ingin merasakan validasi yang dulu membuat kita merasa cukup.
Closure bukan berarti lupa, melainkan berhenti mencari alasan untuk apa yang sudah berlalu. Ketika kita berhenti bertanya, “Kenapa dia tega ninggalin aku?”, dan mulai bilang, “Oh, memang sudah waktunya dia pergi,”—di situlah pintu rumah kenangan mulai terkunci pelan-pelan.
Cara Mengingat Kita Menentukan Seberapa Dalam Luka Itu
Riset dari Sanda Dolcos dan timnya di University of Illinois (2018) menemukan bahwa ketika seseorang terlalu fokus pada aspek emosional dari kenangan—seperti rasa sakit, kecewa, atau kehilangan—otak justru makin memperkuat memori itu. Sebaliknya, jika fokus dialihkan ke konteks (siapa, kapan, di mana, apa yang terjadi), kenangan jadi lebih “netral” dan efek emosionalnya melemah.
Menurut saya, ini seperti menonton ulang film lama. Kalau kamu menontonnya sambil merasa “aku korban di sini”, film itu selalu terasa menyakitkan. Namun, kalau kamu menontonnya dengan jarak, seperti penonton, bukan pemeran utama, kamu bisa melihat hal-hal yang dulu terlewat: kesalahan kecil, tanda-tanda akhir, atau pelajaran yang ternyata penting.
Saya pernah berpikir bahwa move on berarti berhenti mengingat. Namun, setelah membaca riset ini, saya sadar: bukan ingatannya yang harus dihapus, tapi cara kita menatapnya yang perlu diubah. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa mengubah narasinya di kepala. Ketika kita mengganti kalimat “dia ninggalin aku” jadi “sudah waktunya kami selesai”, kita memberi ruang bagi diri untuk berdamai tanpa harus menutup kenangan itu dengan kebencian.
Menghindari Kenangan Justru Membuat Kita Terjebak
Dalam tulisannya di Anxiety and Depression Association of America (ADAA), Barbara O. Rothbaum dan Sheila A.M. Rauch (2023) menjelaskan bahwa orang yang terus menghindari kenangan menyakitkan justru berisiko lebih tinggi mengalami kecemasan dan depresi. Otak menandai kenangan itu sebagai “bahaya”, sehingga setiap kali muncul, reaksi emosionalnya jadi makin kuat.

 2 weeks ago
13
2 weeks ago
13