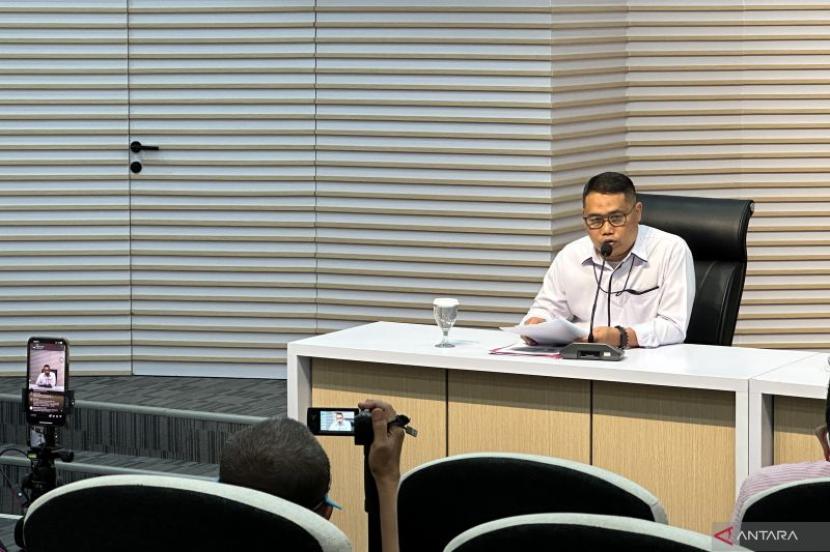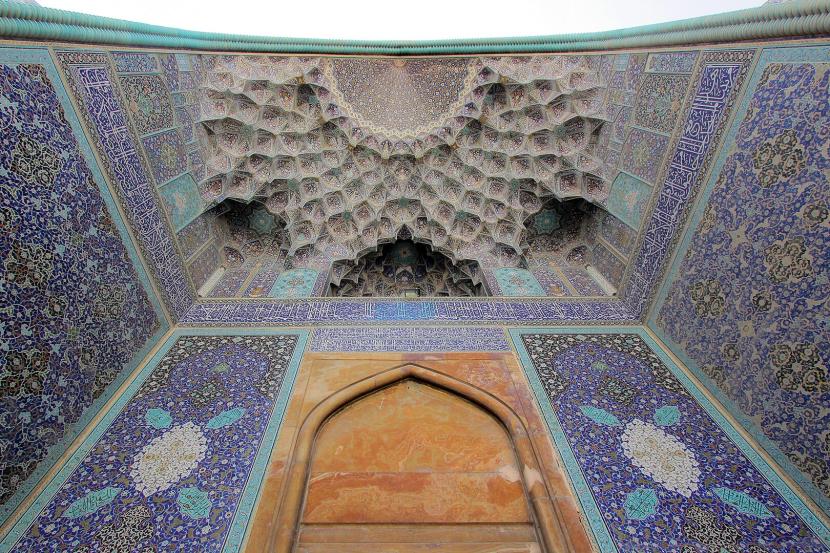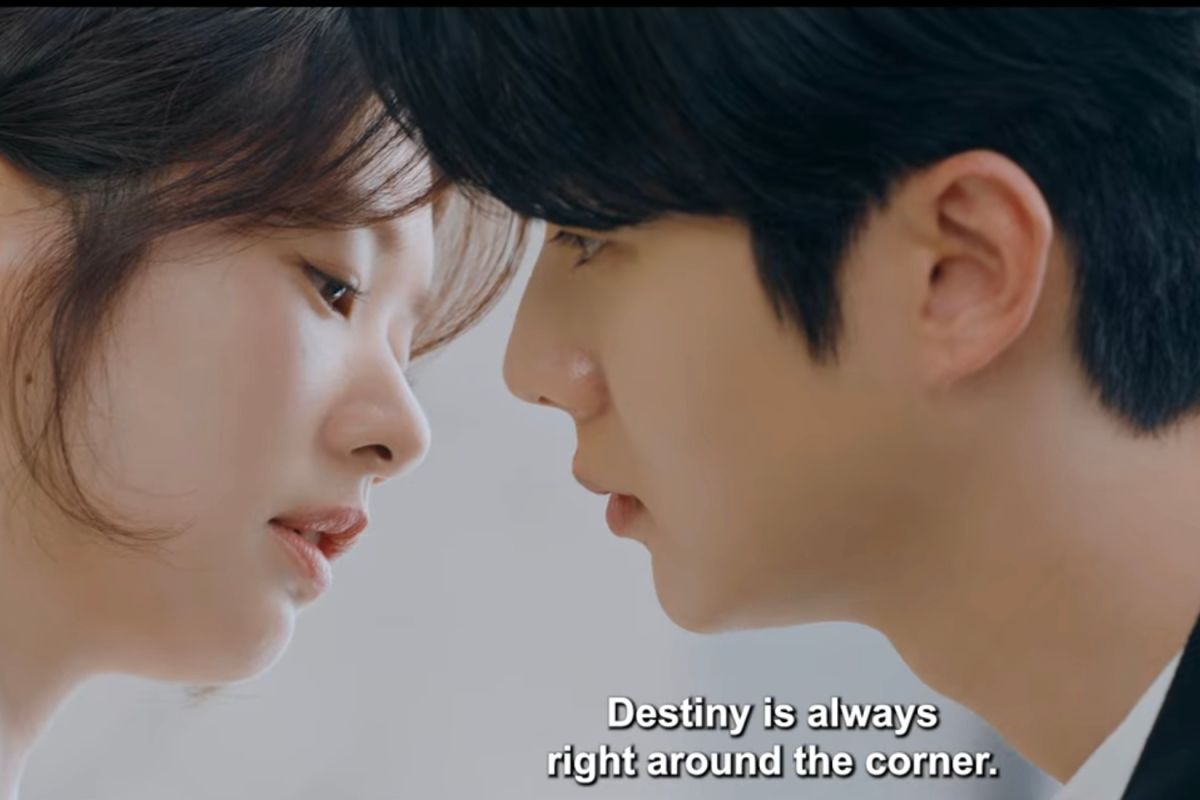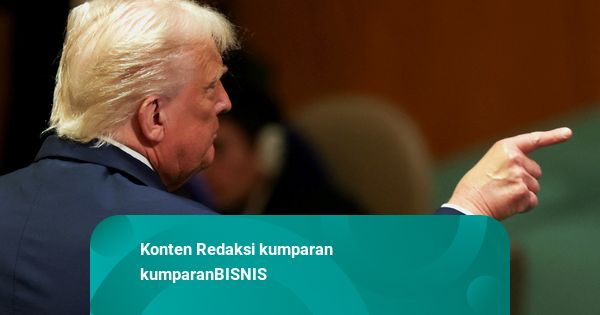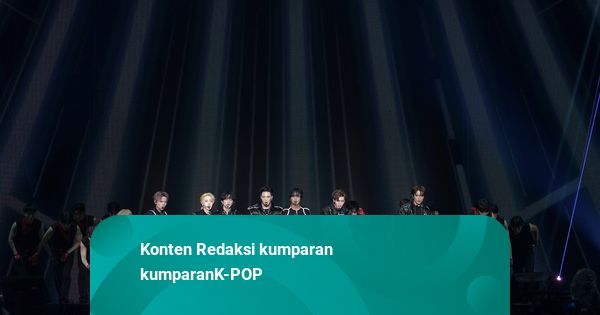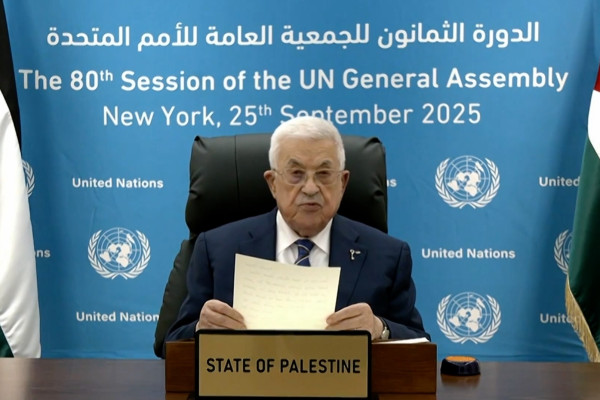Tambak udang kerap menjadi perbincangan hangat ketika membahas pertemuan antara ekonomi biru dan pelestarian lingkungan. Di satu sisi, udang vannamei (Litopenaeus vannamei) telah menjelma sebagai komoditas unggulan Indonesia dengan nilai ekspor mencapai miliaran dolar AS per tahun. Di sisi lain, intensifikasi tambak membawa konsekuensi lingkungan: penurunan kualitas air, akumulasi sedimen organik, hingga hilangnya keanekaragaman hayati bentik pesisir. Pertanyaannya: mungkinkah tambak udang tetap menjadi penopang ekonomi sekaligus pelindung ekosistem pesisir?
Jawabannya ada pada bagaimana pelaku usaha, regulator, dan masyarakat memastikan setiap aktivitas budidaya terkendali, bersih, dan dapat dinetralkan kembali sebelum bersentuhan dengan lingkungan alamiah.
Jejak Ekologis Tambak Udang
Intensifikasi tambak udang identik dengan penggunaan pakan dalam jumlah besar, bahan kimia untuk sterilisasi, serta input energi tinggi. Proses ini memunculkan residu organik berupa feses dan sisa pakan yang mengendap di dasar kolam. Menurut Zhang et al. (2022, Aquaculture), akumulasi organik pada tambak intensif meningkatkan risiko hipoksia dan pembentukan senyawa sulfida yang beracun bagi organisme bentik. Jika tidak ditangani, air buangan tambak bisa mengandung nitrogen, fosfor, dan bahan organik tinggi yang memicu eutrofikasi perairan pesisir.
Namun, praktik tersebut bukan harga mati. Kajian FAO (2023) menegaskan bahwa dengan manajemen input yang cermat, sistem budidaya intensif masih bisa beriringan dengan ekosistem sehat. Kuncinya terletak pada pemilihan bahan ramah lingkungan, proses aplikasi yang tepat, serta sistem pengolahan limbah terpadu.
Dari Air Masuk hingga Air Keluar: Rantai Tanggung Jawab
Pengelolaan lingkungan tambak udang tidak bisa hanya berfokus pada kolam budidaya. Rantai tanggung jawab dimulai sejak air pertama kali masuk hingga akhirnya dilepaskan kembali.
1. Air Input dan Sterilisasi
Air yang masuk ke tambak kerap mengandung plankton liar, patogen, atau bahan organik berlebih. Sterilisasi menjadi tahap penting, biasanya dilakukan dengan bahan kimia seperti kapur atau oksidator. Namun, kecenderungan global kini mendorong penggunaan probiotik, ozon, hingga biofiltrasi yang lebih ramah lingkungan (Li et al., 2021, Marine Pollution Bulletin).
Selama pemeliharaan, kualitas air dikontrol secara ketat: DO (dissolved oxygen), pH, salinitas, dan amonia. Teknologi real-time monitoring mulai diadopsi di banyak tambak modern. Sistem ini memungkinkan deteksi dini kondisi berbahaya, sehingga intervensi bisa dilakukan sebelum terjadi degradasi kualitas lingkungan (Rahman et al., 2023, Aquacultural Engineering).
Inilah tahap paling krusial: memastikan air keluar tidak menjadi 'racun' bagi laut. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) kini dianggap sebagai best practice. Sistem IPAL berbasis kolam sedimentasi, biofilter, hingga wetland buatan mampu menurunkan beban organik secara signifikan (Budiardi et al., 2022, Indonesian Aquaculture Journal). Bahkan, beberapa perusahaan tambak di beberapa daerah sudah mengembangkan recirculating aquaculture system (RAS) untuk meminimalisasi pelepasan limbah ke lingkungan.

 1 month ago
30
1 month ago
30