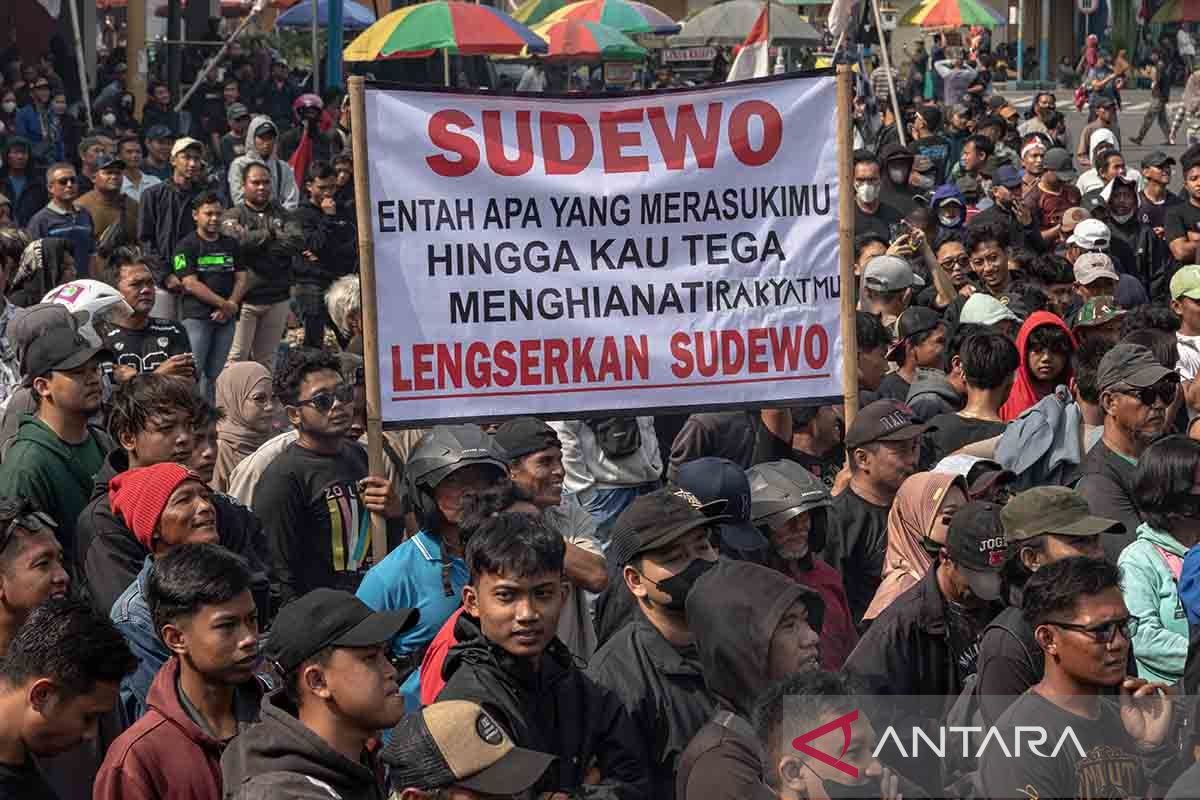Film Avatar (2009) yang disutradarai James Cameron, berisi kisah yang berisi konflik sosial, politik, dan bersinggungan dengan ekologis. Narasi yang dihadirkan berupa logika kolonialisasi manusia yang dilakukan kepada masyarakat adat Na’vi yang hidup berdampingan dengan alam. Kalau kita masukkan referensi dari buku Political Ecology, film ini bukan cuma hiburan, akan tetapi menjadi penekanan bahwa kekuasaan, keadilan, dan lingkungan saling berkaitan dengan konflik sumber daya. Cerita yang dihadirkan pada film Avatar itu juga terjadi pada dunia nyata khususnya pada masyarakat adat yang ada di dunia. Di film, manusia berusaha menambang unobtainium dengan menggusur tanah yang dimiliki Na’vi, dan hal tersebut jadi gambaran gimana kapitalisme ekstraktif merampas tanah, merusak lingkungan, dan mengabaikan hak komunitas lokal. Sama seperti yang dinyatakan pada political ecology yaitu “power, justice and environmental sustainability” menjadi isu utama, Na’vi digambarkan sebagai penjaga keseimbangan ekologis Pandora, sedangkan manusia mewakili logika ekspansi kapitalistik.
Ini bisa dijadikan gambaran tentang negara-negara Global South mengalami ketimpangan untuk memperbaiki lingkungan dan masih ketergantungan bantuan bahkan narasi dari Global North. Kalau dia analogikan di film Avatar maka menjadi, Na’vi (Global South) tidak bisa melawan kalau tidak dibantu orang kulit putih (Global North) tersebut. Krisis iklim memperlihatkan realita ketimpangan, dimana negara-megara Global South menjadi pihak paling rentan seperti terancam naiknya permukaan air laut, bencana akibat perubahan iklim, dan kerusakan ekosistem lingkunga. Dengan kata lain, struktur dunia yang ada sekarang menempatkan Global North sebagai penghasil masalah, sementara Global South menanggung beban atas dampak-dampaknya.
Hal tersebut dapat dijelaskan melalui teori strukturalisme yang melihat bahwa negara-negara industri maju (core) menguasai teknologi, modal, sampai pengampilan keputusan. Dan negara pinggiran (periphery) yang menjadi penyedia bahan mentah, tenaga kerja murah, sekaligus menanggung dampak lingkungan dari industrialisasi. Tata kelola iklim global hingga mekanisme seperti perdagangan karbon banyak yang dikuasai kepentingan negara maju. Negara-negara Global North sering tampil jadi pemimpin diplomasi iklim. Solusi seperti carbon trading atau investasi transisi energi tetap ujung-ujungnya menguntungkan perusahaan multinasional dari Global North. Dan dari perspektif strukturalis, solusi tersebut tidak menyelesaikan akar masalah dan justru melanggengkan ketergantungan dengan Global South terlebih dengan modal, teknologi, dan narasi.
Dalam kerangka strukturalis maka penyelesaian yang ditawarkan adalah Global North harus menanggung tanggung jawab historis melalui kompensasi dan bukan pinjaman/investasi bersyarat sehingga tidak menciptakan ketergantungan. Lalu memberikan ruang pada masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan karena merekalah yang menerima dampak akibat ekploitasi tersebut. Dan memulai kolaborasi antarnegara Global South untuk teknologi hijau dan transisi energi sehingga juga turut berkontribusi dalam SDGs 17.
Strukturalisme mengingatkan kita bahwa solusi iklim sejati harus membongkar ketergantungan, mengembalikan kedaulatan ekologis pada Global South, dan menempatkan keadilan sebagai fondasi. Tanpa itu, dunia hanya akan mengulang pola Pandora: krisis ekologis yang diciptakan pusat, sementara pinggiran terus menjadi korban.

 1 week ago
11
1 week ago
11