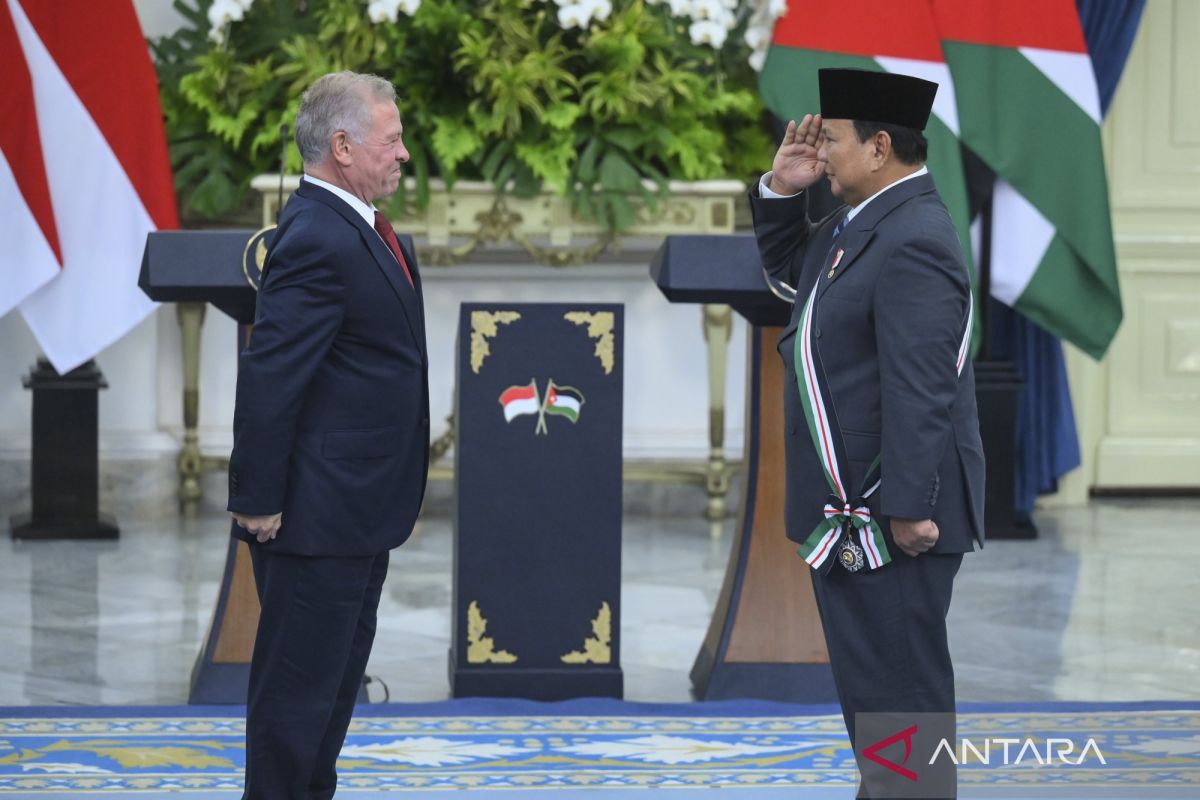Jika dulu kita terbiasa melihat nama seseorang diakhiri dengan deret singkat gelar akademik formal—seperti S.E., M.Hum., atau Ph.D.—kini kita disuguhi fenomena baru, sebuah etalase singkatan yang jauh lebih panjang, asing, dan membingungkan. Dari Certified Hypnotherapist (CHT) hingga Chartered Human Resources Manager (CHRM), dari Certified Financial Planner (CFP) hingga Certified Master (CM), singkatan-singkatan ini menempel erat di belakang nama, baik di kartu nama, papan nama kantor, maupun ruang digital seperti profil profesional di LinkedIn.
Fenomena ini bukan sekadar tren, melainkan sebuah manifestasi dari apa yang dapat kita sebut sebagai “Eforia Simbolik” dan telah memicu inflasi gelar (title inflation) di tengah masyarakat. Sertifikasi, yang seharusnya menjadi alat internal untuk memvalidasi kompetensi spesifik, kini bertransformasi menjadi status sosial baru yang diperjuangkan untuk ditampilkan gelarnya.
Inti masalahnya adalah terletak pada pergeseran nilai. Gelar akademik formal adalah produk dari proses panjang, terstandardisasi, dan diakui oleh negara. Sebaliknya, singkatan sertifikasi lahir dari sistem micro-credentialing yang sering kali bersifat swasta, cepat, dan spesifik. Gelar tersebut menjadi bukti telah menyelesaikan kursus atau pelatihan, bukan gelar yang diperoleh dari jenjang pendidikan tinggi.
Namun, di tengah masyarakat yang cenderung mengutamakan simbol ketimbang substansi, sertifikasi tersebut diperlakukan setara dengan gelar formal. Semakin banyak sertifikasi yang dicantumkan, seolah semakin tinggi nilai pasar profesional seseorang. Dalam arena kompetisi kerja yang kian sengit, penambahan singkatan sertifikasi dipandang sebagai pendongkrak kredibilitas yang sifatnya instan.
Inflasi gelar ini menciptakan devaluasi simbolik. Ketika setiap orang dapat dengan mudah mencantumkan singkatan yang terlihat impresif—bahkan setelah mengikuti pelatihan daring singkat—nilai intrinsik dari gelar-gelar yang diperoleh melalui perjuangan akademik dan profesional yang sesungguhnya menjadi kabur. Publik kesulitan membedakan mana akreditasi yang dikeluarkan oleh otoritas negara (seperti BNSP) yang menjamin standar kompetensi yang ketat, dan mana singkatan yang hanya mewakili keanggotaan atau kelulusan kursus biasa. Kebingungan ini berpotensi menjadi masalah etika dan legalitas.
Obsesi masyarakat terhadap pencantuman gelar sertifikasi bukanlah sekadar tren profesional semata, melainkan refleksi dari akar budaya Indonesia yang mendalam, yaitu penghargaan berlebihan terhadap simbol status. Fenomena ini dapat disebut sebagai sebagai “Budaya Titelisasi,” yaitu sebuah perilaku kolektif yang menganggap gelar (baik akademik, profesi, maupun sertifikasi) sebagai instrumen vital validasi sosial dan penentu hierarki di ruang publik. “Budaya Titelisasi” ini mengubah sertifikasi dari sebuah instrumen peningkatan kompetensi menjadi sebuah perlombaan simbolik. Perlombaan yang, jika tidak diatur, hanya akan menghasilkan deretan nama panjang yang secara substansial kosong, dan secara regulatif, menciptakan kekacauan makna gelar di ruang publik.
Ketika kita membahas pencantuman gelar, wajib hukumnya untuk kembali kepada payung hukum tertinggi yang mengatur masalah ini, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). UU Sisdiknas dan regulasi turunannya (seperti Peraturan Menteri) memberikan mandat yuridis yang eksklusif dan ketat mengenai siapa saja yang berhak memberikan gelar, jenis gelar, dan bagaimana gelar tersebut digunakan.
Menurut UU Sisdiknas, gelar akademik didefinisikan secara jelas sebagai gelar yang diberikan oleh Perguruan Tinggi kepada lulusan yang telah menyelesaikan program pendidikan akademik atau program pendidikan profesi. Gelar-gelar ini terbagi atas jenjang Vokasi (A.Md.), Sarjana (S.), Magister (M.), dan Doktor (Dr.), serta gelar profesi tertentu yang diakui oleh negara.
Penting untuk digarisbawahi, otoritas pemberian gelar akademik bersifat tunggal dan terpusat. Gelar tersebut bukan sekadar simbol yang dijualbelikan atau didapat dari pelatihan singkat; ia adalah pengakuan formal dari negara melalui institusi pendidikan yang terakreditasi, yang menjamin bahwa penerimanya telah melewati kurikulum yang ketat, ujian yang terstandardisasi, dan, yang terpenting, telah menyelesaikan riset orisinal (misalnya, skripsi, tesis, atau disertasi).
Setiap penggunaan gelar akademik harus diverifikasi dan dicatat dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), menjadikannya aset personal yang dilindungi undang-undang. Pencantuman gelar yang tidak sah atau palsu dapat dikenai sanksi pidana, sebuah indikasi seberapa serius negara melindungi integritas simbol-simbol pengakuan ini.
Di sinilah letak jurang pemisah fundamental antara gelar akademik/profesi resmi dengan singkatan sertifikasi (CHT, CM, dsb.). Gelar sertifikasi, sekalipun dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atau lembaga independen yang terkemuka, secara tegas bukan merupakan gelar akademik dalam definisi UU Sisdiknas. Sertifikasi adalah bukti kompetensi terapan, sementara gelar akademik adalah bukti pencapaian dalam jenjang pendidikan tinggi.
Sertifikasi umumnya dikeluarkan oleh lembaga pelatihan, asosiasi swasta, atau korporasi. Lembaga-lembaga ini tidak memiliki otoritas akademik yang diakui negara untuk memberikan gelar, sehingga singkatan yang mereka berikan hanya memiliki legalitas internal secara institusional atau legalitas pasar, bukan kedudukan huku...

 1 month ago
22
1 month ago
22