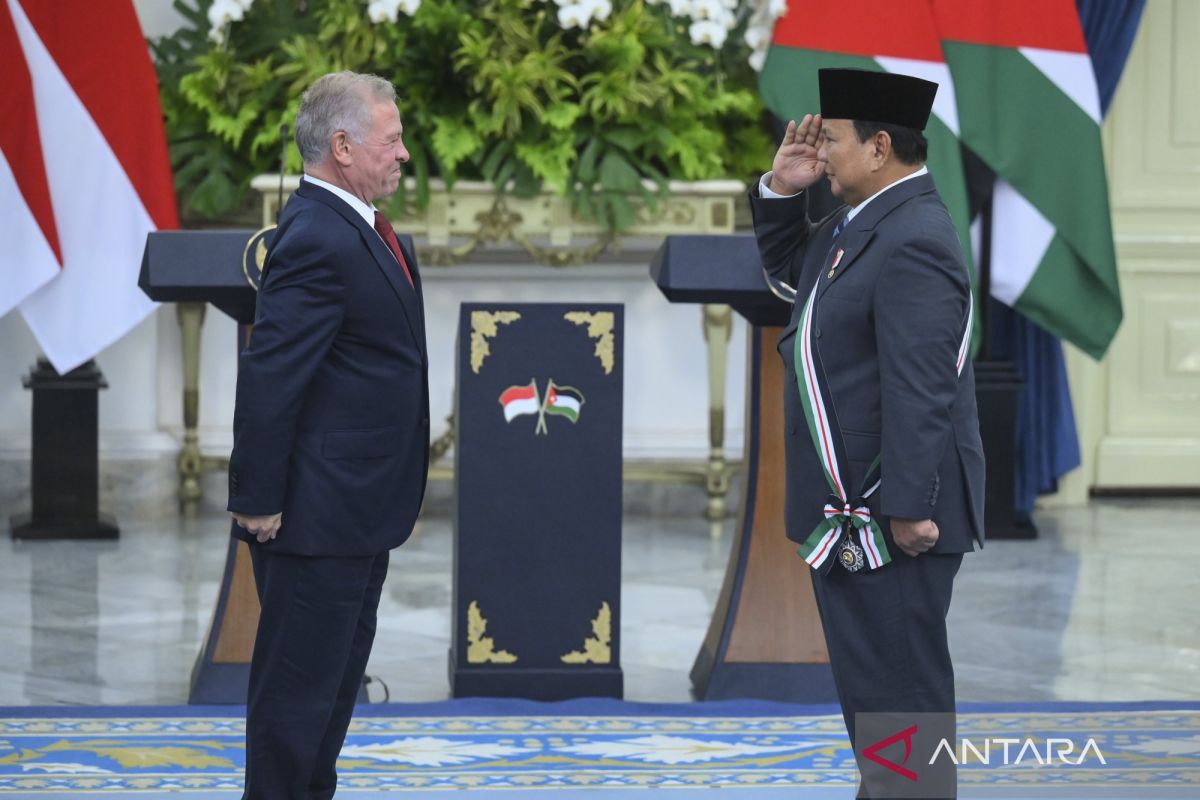Di banyak kota, pagi hari dimulai dengan mesin mobil yang dianaskan lebih dulu daripada air untuk menyeduh kopi. Orang-orang berangkat sambil menunduk ke layar ponsel, melewatkan kesempatan menyapa tetangga yang berdiri di pagar rumah. Sarapan sering dikalahkan oleh rapat, dan obrolan diganti notifikasi.
Di tengah ritme seperti itu, kota yang bergerak pelan kerap dicurigai: jangan-jangan warganya kurang ambisius. Kediri sering ditempatkan dalam kecurigaan semacam itu. Ritme hidupnya tidak tergesa. Orang-orangnya masih terlihat duduk lama di warung, mengobrol tanpa jam di tangan.
Justru kota seperti Kediri, kita bisa bercermin tentang satu pertanyaan yang lebih mendasar: apakah ambisi selalu harus berisik untuk bisa bermakna?
Lantai ubin warung pecel punten itu terasa dingin di bawah alas kaki. Aroma gurih santan dari punten yang dipotong kotak-kotak berpadu dengan wangi daun jeruk dari sambal pecel yang kental. Di atas meja panjang tampak piring-piring penuh dengan sayuran hijau, kerupuk pasir, dan rempeyek yang renyah.
Orang-orang duduk di bangku kayu, dan sebagian lesehan saling bersisian tanpa jarak sosial yang kaku. Tidak ada yang terburu-buru. Tidak ada yang merasa perlu mendahului.
Seorang ibu di balik meja sibuk menata pincuk. Tangannya lincah, geraknya hafal betul urutan kerja yang sama ia ulang setiap hari. Saat pembayaran selesai, ia tersenyum sambil menerima lembaran uang.
“Matur nuwun, benjing mriki maleh nggeh,” ucapnya ringan, seolah kalimat itu bukan basa-basi, melainkan janji kecil yang tulus. Kalimat yang sama ia ucapkan pada setiap orang yang melangkah keluar menuju parkiran motor yang padat.
Di balik piring-piring punten itu, ada semacam kesepakatan tak tertulis untuk tidak saling memburu. Orang-orang datang bukan sekadar untuk kenyang, melainkan untuk berhenti sejenak dari urusan kerja, target, atau cicilan.
Kalimat “Besok ke sini lagi ya” terdengar seperti pengingat bahwa hidup tidak harus selalu meloncat jauh. Selama hari ini bisa makan dengan tenang dan besok masih punya alasan untuk kembali, itu sudah cukup.
Di sinilah pertanyaan itu muncul: apakah warga Kediri tidak ambisius?
Pertanyaan ini sering muncul dari cara pandang luar. Kota yang ritmenya tenang, orang-orangnya tidak tampak tergesa, jarang memamerkan pencapaian, dan tampak nyaman dengan rutinitas yang itu-itu saja. Dalam logika kota besar, ketenangan semacam ini sering dibaca sebagai kurang greget, atau kurang daya saing.
Namun penilaian itu lahir dari definisi ambisi yang sempit: ambisi yang selalu bising, terlihat, dan menuntut pengakuan.
Di Kediri, ambisi dijalani dengan napas panjang. Tidak ada dorongan untuk selalu "lebih" dari orang lain. Yang dijaga justru keberlanjutan, agar kerja hari ini tidak mencuri ketenangan untuk esok hari.
Prasojo sebagai Etika Sosial, Bukan Sekadar Sikap Pribadi
Warga Kediri mengenal konsep lain yang lebih tua dan lebih dalam: prasojo. Dalam filosofi Jawa, prasojo sering diterjemahkan sebagai “sederhana”. Tapi makna itu kerap tereduksi. Prasojo bukan berarti tidak mampu, tidak punya target, atau pasrah pada keadaan. Read Entire Article

 2 days ago
5
2 days ago
5