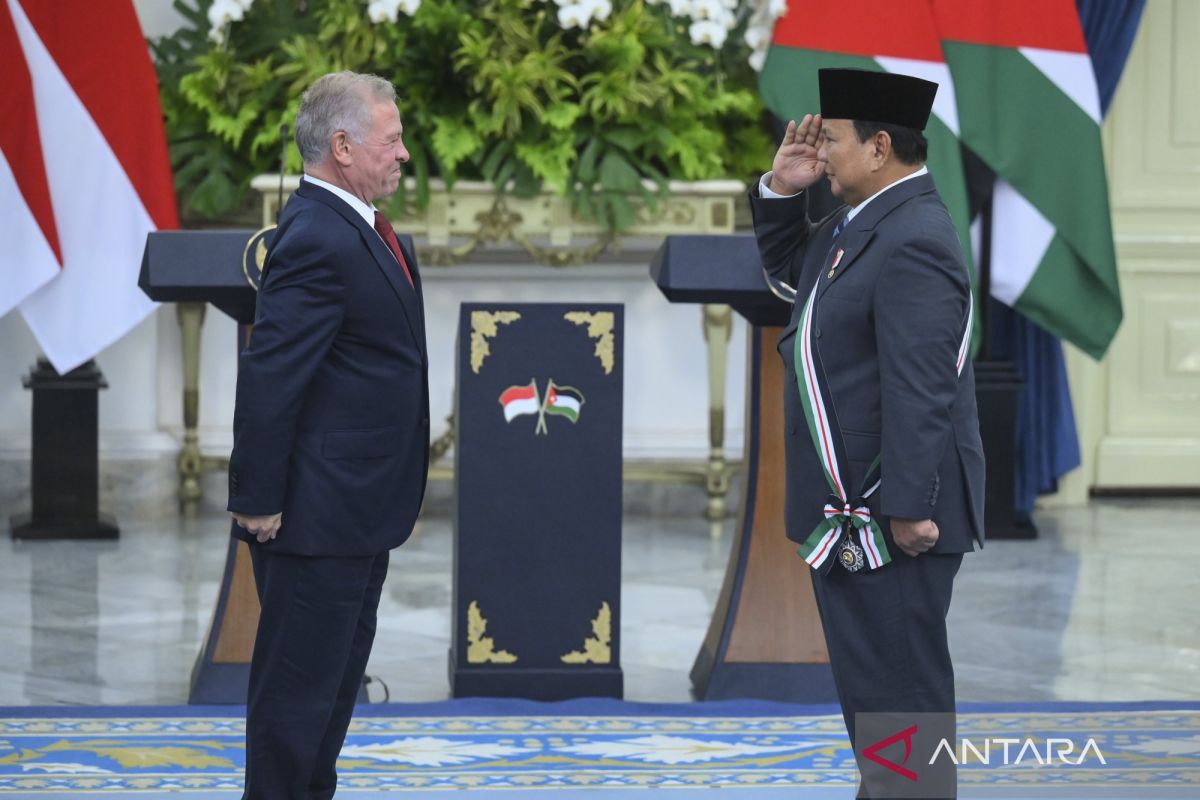Konflik Yaman yang telah berlangsung hampir satu dekade, kembali memasuki fase paling berbahaya sepanjang 2025. Di tengah gencatan senjata rapuh yang bertahan sekitar tiga setengah tahun, justru muncul eskalasi baru yang bersumber dari konflik internal di dalam kubu anti-Houthi. Fenomena ini menandai apa yang dapat disebut sebagai “perang di dalam perang”, yakni konflik bersenjata yang terjadi di antara sekutu formal yang sebelumnya berada dalam satu koalisi militer.
Retaknya relasi antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) di Yaman memperlihatkan kegagalan mendasar dalam manajemen aliansi keamanan regional. Dalam perspektif teori pertahanan nasional, konflik ini bukan semata kegagalan taktis, melainkan kegagalan strategis dalam menyelaraskan kepentingan nasional, ancaman eksternal, dan desain keamanan kolektif di kawasan Timur Tengah.
Akar konflik Yaman bermula dari ketidakstabilan pasca-Arab Spring 2011, yang memperlemah negara dan membuka ruang bagi aktor non-negara bersenjata. Kejatuhan Presiden Ali Abdullah Saleh dan transisi kekuasaan kepada Abdurabbuh Mansur Hadi, gagal menciptakan konsolidasi politik. Ketika kelompok Houthi merebut Sanaa pada 2014, Yaman secara efektif memasuki fase state collapse.
Arab Saudi membentuk koalisi militer pada 2015 dengan tujuan memulihkan pemerintahan Hadi dan menahan pengaruh Iran. Dalam kerangka defensive realism, Saudi memandang Yaman sebagai buffer zone vital bagi keamanan nasionalnya. Ancaman bukan hanya ideologis atau sektarian, tetapi bersifat struktural terhadap stabilitas perbatasan selatan kerajaan.
Namun, pendekatan pertahanan Saudi sejak awal mengandalkan kekuatan militer koersif. Serangan udara masif, blokade laut, dan tekanan ekonomi. Strategi ini mengabaikan dimensi human security yang menjadi pilar utama studi perdamaian modern. Akibatnya, konflik Yaman berkembang menjadi salah satu krisis kemanusiaan terburuk abad ke-21, tanpa membawa Saudi lebih dekat pada kemenangan strategis.
Bagi Mohammad bin Salman, konflik Yaman juga berfungsi sebagai instrumen konsolidasi kekuasaan domestik. Dalam teori pertahanan nasional, ini mencerminkan penggunaan konflik eksternal untuk legitimasi internal. Namun, kalkulasi tersebut keliru karena perang justru memperkuat posisi Houthi dan memperdalam ketergantungan mereka pada Iran.
Di sisi lain, UEA memiliki kalkulasi geopolitik yang berbeda. Abu Dhabi tidak semata mengejar stabilitas Yaman secara nasional, melainkan kepentingan maritim, pelabuhan strategis, dan pengaruh politik di wilayah selatan. Dukungan terhadap Dewan Transisi Selatan (STC) mencerminkan strategi proxy governance dalam kerangka keamanan regional.
Ketegangan memuncak pada akhir Desember 2025 ketika STC, dengan dukungan UEA, merebut wilayah strategis Hadramawt dan Mahrah. Dalam perspektif geopolitik, wilayah ini sangat krusial karena kaya minyak, relatif aman dari serangan Houthi, dan menjadi pintu menuju Samudra Hindia. Penguasaan wilayah ini mengubah keseimbangan kekuatan di Yaman selatan.
Arab Saudi memandang langkah STC sebagai pelanggaran langsung terhadap keamanan nasionalnya. Dalam doktrin pertahanan nasional Saudi, wilayah perbatasan selatan merupakan red line. Tuduhan bahwa UEA mengirim senjata melalui Pelabuhan Mukalla menandai pergeseran relasi dari koalisi strategis menuju kompetisi keamanan terbuka.
Penarikan resmi pasukan UEA sejak 2019 tidak berarti pelepasan pengaruh. Justru, pendekatan light footprint memungkinkan Abu Dhabi mempertahankan kendali melalui aktor lokal tanpa menanggung biaya politik internasional. Ini sejalan dengan teori konflik modern yang menekankan pergeseran dari perang antarnegara menuju konflik hibrida dan proksi.
Dari sudut pandang studi perdamaian, konflik Saudi–UEA di Yaman menunjukkan kegagalan negative peace. Absennya perang terbuka antarnegara tidak berarti terciptanya perdamaian substantif. Justru, kekerasan terfragmentasi dan kompetisi proksi memperpanjang penderitaan sipil dan melemahkan peluang rekonsiliasi nasional Yaman.
Kepentingan energi turut memperumit konflik. Ambisi Saudi membangun jalur pipa minyak melalui Al Mahra menuju Samudra Hindia merupakan kalkulasi strategis untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Namun, proyek ini justru memicu resistensi lokal dan memperkuat konflik horizontal, bertentangan dengan prinsip sustainable security.
Sementara itu, respons negara-negara Teluk lain seperti Kuwait, Bahrain, dan Qatar mencerminkan kekhawatiran terhadap fragmentasi keamanan regional. Dukungan mereka terhadap dialog politik menunjukkan kesadaran bahwa konflik Yaman telah melampaui kapasitas solusi militer dan berpotensi merusak arsitektur keamanan Teluk secara keseluruhan.

 1 week ago
21
1 week ago
21