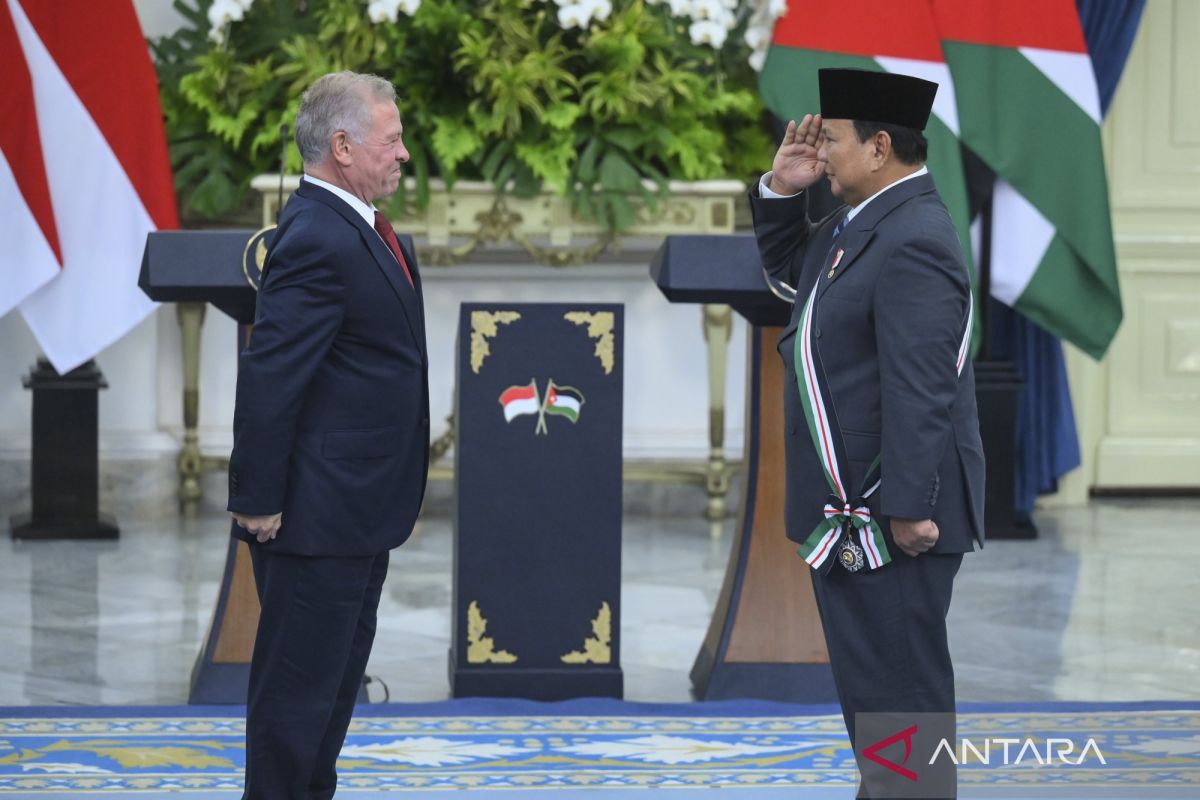Pada awal kemunculannya, ruang digital terasa seperti surga kebebasan. Semua orang bisa bicara, bersuara, dan didengar tanpa harus punya jabatan, modal besar, atau koneksi elite. Dunia maya seolah meruntuhkan batas geografis dan hierarki sosial.
Gerakan #MeToo yang dimulai sejak 2006 mengubah percakapan global tentang kekerasan berbasis gender. Media sosial kala itu menjelma menjadi ruang aman tempat perempuan berbagi pengalaman pahit yang selama ini terpaksa disimpan rapat-rapat.
Tarana Burke dalam Me Too Movement (2018) menyebut solidaritas digital sebagai kekuatan yang menumbuhkan keberanian kolektif. Twitter (sekarang X) pun berubah menjadi panggung global bagi suara perempuan dari berbagai belahan dunia. Kesaksian demi kesaksian menciptakan tekanan sosial nyata.
Kasus Harvey Weinstein menjadi bukti bahwa suara kolektif perempuan mampu mengguncang struktur kekuasaan yang selama ini terasa kebal. Pada masa itu, teknologi benar-benar terasa berpihak pada keadilan gender.
Sayangnya, euforia itu tidak bertahan lama. Ruang digital yang dulu terasa aman kini berubah menjadi ladang ancaman. Teknologi melesat jauh lebih cepat dibanding etika sosial penggunanya.
Institute of Development Studies melalui laporan "Online Violence Against Women" (2021) mencatat eskalasi kekerasan digital secara global. Bentuk kekerasannya kini bukan cuma satu dua, melainkan lebih dari empat puluh jenis. Mulai dari pelecehan verbal, ancaman, doxing, manipulasi, hingga peretasan akun. Media digital pun berubah menjadi ruang yang melelahkan secara emosional. Optimisme digital perlahan bergeser menjadi kecemasan struktural.
Kekerasan berbasis gender yang difasilitasi teknologi atau Technology-Facilitated Gender-Based Violence (TFGBV) menjadi persoalan utama. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan bahwa dampaknya sangat luas.
Head of Programmes UN Women Indonesia, Dwi Yuliawati, menjelaskan bahwa TFGBV merugikan perempuan secara fisik, sosial, bahkan politik. Dalam UNiTE Campaign Brief (2024), disebutkan bahwa kekerasan ini menghambat partisipasi publik perempuan. Dunia virtual ternyata tidak netral. Ia justru memperpanjang kekerasan dunia nyata dan perlahan menggerus rasa aman perempuan.
Akar persoalannya bukan hal baru: misogini. Kate Manne dalam Down Girl (2018) menjelaskan misogini sebagai sistem penghukuman sosial. Sistem ini bekerja untuk “menertibkan” perempuan yang dianggap melampaui batas yang ditentukan.
Di dunia digital, sistem ini diperkuat oleh algoritma. Komunitas manosphere tumbuh subur dan menyebarkan kebencian terhadap perempuan secara sistematis. Teknologi—alih-alih netral—justru mempercepat penyebaran ide-ide diskriminatif. Ketimpangan kuasa makin terang terlihat di ruang virtual.
Situasi menjadi semakin rumit dengan hadirnya kecerdasan buatan. Pornografi deepfake muncul sebagai ancaman serius. Security Hero dalam Deepfake Report (2023) mencatat lonjakan konten deepfake hingga 550 persen.
Yang lebih mengkhawatirkan, sebanyak 98 persen korbannya adalah perempuan. Wajah dimanipulasi tanpa persetujuan. Identitas digital dirampas begitu saja. AI membuat pelaku semakin sulit dilacak. Kekerasan ini memang tanpa sentuhan fisik, tetapi dampaknya bisa menghancurkan hidup seseorang.

 1 week ago
21
1 week ago
21