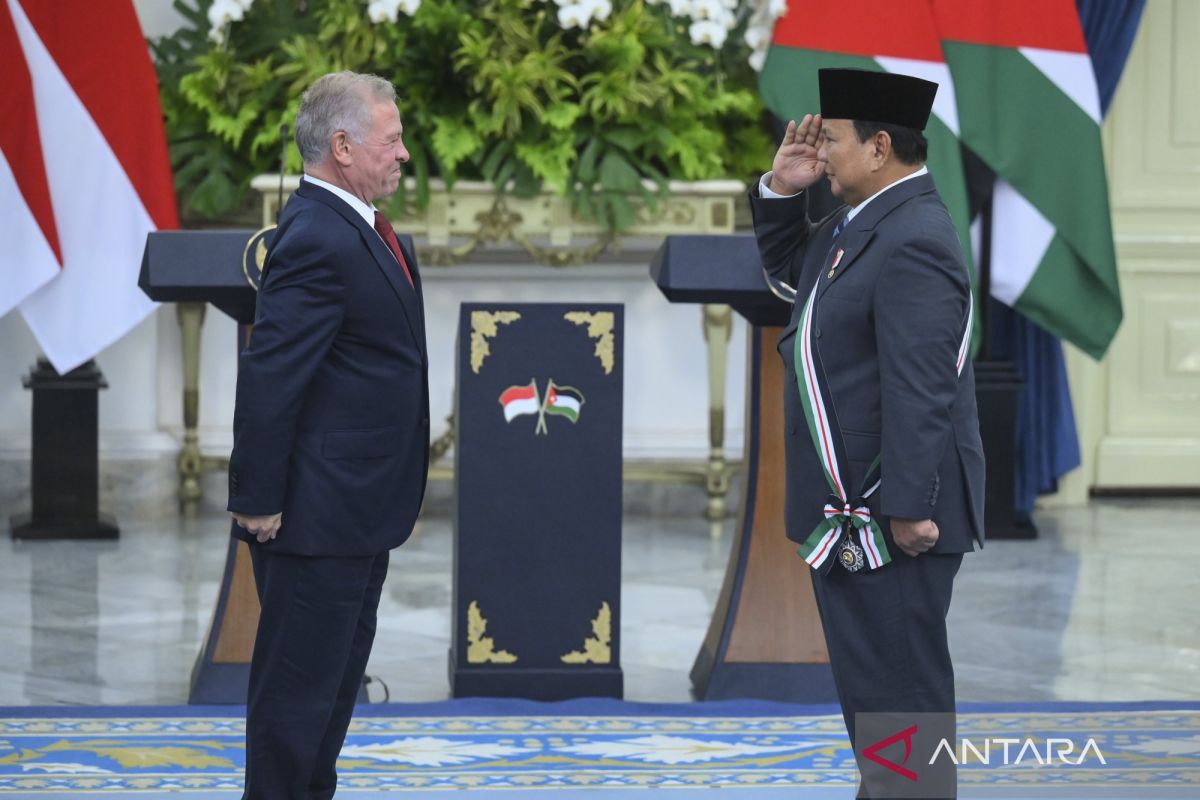Ketegangan diplomatik antara Amerika Serikat dan Venezuela kembali mengemuka setelah Caracas mengumumkan pengerahan militer besar-besaran pada Selasa (11/11/2025). Langkah itu diambil sebagai respons atas kehadiran armada laut dan udara Amerika Serikat di lepas pantai Venezuela. Pemerintah di bawah Presiden Nicolas Maduro menyebut pengerahan ini mencakup seluruh matra: angkatan darat, laut, udara, pasukan sungai, satuan rudal, dan milisi sipil. Ketegangan ini menandai babak baru dalam rivalitas lama antara Washington dan Caracas, yang kini berkembang menjadi potensi krisis militer di jantung kawasan Amerika Latin.
Amerika Serikat berdalih bahwa kehadiran militernya di kawasan Karibia merupakan bagian dari operasi antinarkotika global. Gugus tugas yang melibatkan kapal induk USS Gerald R. Ford, enam kapal perang, serta jet tempur siluman F-35 ditempatkan di Puerto Rico dan perairan Karibia. Namun, operasi yang diklaim untuk memberantas kartel narkoba ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pengamat internasional. Sebab, hingga kini belum ada bukti publik yang menunjukkan bahwa kapal-kapal yang diserang benar-benar terkait dengan penyelundupan narkoba.
Bagi Venezuela, manuver militer Amerika Serikat adalah bentuk provokasi yang nyata. Pemerintah Caracas melihat langkah Washington sebagai upaya menciptakan ketidakstabilan dan menggoyang pemerintahan Maduro yang berhaluan kiri. Ketegangan meningkat setelah Menteri Dalam Negeri Venezuela, Diosdado Cabello, menyebut pihaknya berhasil menggagalkan rencana serangan terhadap kapal perang AS, USS Gravely. Serangan tersebut, menurut Caracas, didanai oleh CIA untuk memancing konflik terbuka di perairan Karibia selatan.
Langkah militer AS ini mencerminkan pola lama kebijakan luar negeri Washington yang kerap menggunakan alasan moral atau keamanan global untuk memperluas pengaruh geopolitiknya. Sejak era Perang Dingin, Amerika Serikat telah berkali-kali mengintervensi kawasan yang dianggap strategis, dari Amerika Tengah, Timur Tengah, hingga Asia Tenggara. Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, pola lama itu muncul kembali—dengan Karibia sebagai panggung terbaru.
Maduro menuduh pemerintahan Trump “menciptakan perang” untuk menggulingkannya. Pernyataan Trump pada 2 November 2025 bahwa “hari-hari Maduro sudah selesai” semakin mempertegas aroma perubahan rezim yang menjadi ciri khas intervensi Amerika Serikat. Meskipun Trump menegaskan tidak berniat berperang, tindakan militer di lapangan justru menunjukkan arah sebaliknya.
Situasi ini berpotensi mengancam stabilitas ekonomi global. Venezuela adalah negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Jika konflik bersenjata benar-benar meletus, dampaknya akan merembet ke pasar energi internasional, memicu lonjakan harga minyak, dan mengguncang keseimbangan geopolitik energi antara Rusia, China, dan Amerika Serikat.
Lebih dari itu, konflik ini menunjukkan bahwa Washington belum melepaskan tradisi geopolitik hegemonik yang selalu berupaya menegaskan dominasi di kawasan Amerika Latin—wilayah yang oleh doktrin Monroe sejak abad ke-19 dianggap sebagai “halaman belakang” Amerika Serikat. Di bawah Trump, doktrin itu tampak dihidupkan kembali dalam bentuk modern: intervensi bersenjata dengan dalih perang terhadap kartel narkotika.
Venezuela tak sendiri. Dukungan dari Rusia, China, dan Iran menjadi penyeimbang strategis yang mengubah konstelasi kekuatan regional. Moskow, yang selama ini menjadi sekutu utama Caracas, telah mengirimkan penasihat militer dan sistem pertahanan udara canggih. Beijing, sementara itu, menawarkan bantuan ekonomi dan teknologi dalam menghadapi sanksi ekonomi AS. Iran, di sisi lain, menyediakan dukungan intelijen dan logistik.
Konstelasi ini memperlihatkan bahwa konflik Venezuela-AS bukan semata urusan bilateral, melainkan bagian dari persaingan global yang lebih besar antara blok Barat dan Timur. Jika konflik berkembang, Karibia dapat menjadi medan baru dari perang proksi antara kekuatan besar dunia, layaknya Ukraina di Eropa atau Suriah di Timur Tengah.
Dalam konteks hubungan internasional, fenomena ini menegaskan bahwa Amerika Serikat tetap berperan sebagai global agitator—negara yang, dengan dalih menjaga stabilitas dunia, justru sering kali menciptakan instabilitas baru. Tradisi ini dapat ditelusuri dari intervensi di Irak, Afghanistan, Libya, hingga sanksi terhadap Iran dan Korea Utara. Kini, pola itu menjalar ke kawasan Amerika sendiri.
Kebijakan Trump yang agresif juga menunjukkan transformasi dari soft power diplomacy ke coercive diplomacy. Pendekatan diplomatik yang dulu mengandalkan ekonomi dan ideologi kini bergeser menjadi tekanan militer dan ancaman langsung. Hal ini memunculkan kekhawatiran akan terjadinya militarization of diplomacy, di mana dialog antarnegara semakin digantikan oleh demonstrasi kekuatan.
Venezuela, meskipun lemah secara ekonomi, memiliki kekuatan simbolik sebagai simbol perlawanan terhadap hegemoni Barat di Amerika Selatan. Pengerahan militer besar-besaran oleh Caracas bukan semata upaya pertahanan, tetapi juga pesan politik kepada dunia: bahwa kedaulatan nasional tetap harus dijaga meski menghadapi tekanan global superpower.
Krisis ini juga memperlihatkan perubahan...

 1 month ago
25
1 month ago
25