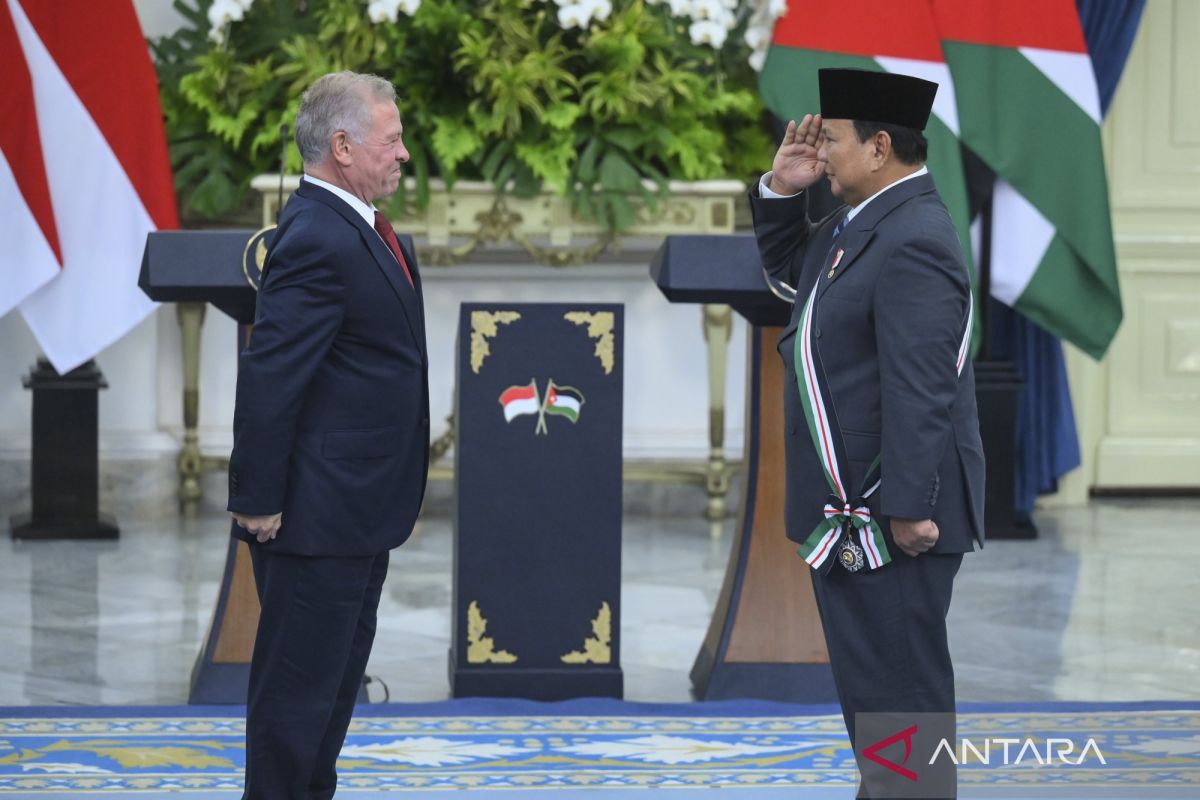Anak tunggal sering hadir dalam percakapan sosial sebagai objek penilaian, bukan sebagai subjek yang didengar. Kami kerap dibicarakan melalui stigma: terlalu dimanjakan, kurang empati, atau tidak terbiasa berbagi. Narasi ini berulang dari generasi ke generasi, seolah status anak tunggal otomatis menentukan kualitas kepribadian seseorang. Padahal, di balik label tersebut, ada pengalaman hidup yang jauh lebih berlapis dan tidak sesederhana itu.
Sebagai mahasiswa yang tumbuh tanpa saudara kandung, saya menyadari bahwa menjadi anak tunggal bukan hanya tentang jumlah anggota keluarga, tetapi tentang bagaimana seseorang belajar memahami dunia dari ruang yang terbatas. Tidak ada kakak yang lebih dulu membuka jalan, tidak ada adik yang harus dijaga. Banyak proses tumbuh terjadi dalam diam—tanpa perbandingan, tanpa persaingan domestik, dan sering kali tanpa tempat berbagi yang setara.
Di satu sisi, anak tunggal memang memperoleh perhatian penuh dari orang tua. Namun perhatian yang utuh ini kerap disertai harapan yang juga utuh. Anak tunggal sering menjadi satu-satunya tempat bergantung, satu-satunya penerus, dan satu-satunya cermin keberhasilan keluarga. Tekanan semacam ini jarang terlihat, karena dibungkus dalam narasi “keberuntungan”. Padahal, tidak semua anak mampu mengelola ekspektasi besar sendirian.
Kesepian menjadi pengalaman yang tidak terhindarkan. Bukan kesepian karena ditinggalkan, melainkan kesepian karena terbiasa sendiri. Banyak anak tunggal tumbuh dengan dunia batin yang padat—penuh dialog internal, imajinasi, dan refleksi. Kami belajar mengisi waktu sendiri, mengambil keputusan sendiri, dan menyelesaikan konflik tanpa mediator saudara. Proses ini sering membentuk kemandirian, tetapi juga menuntut ketahanan emosional yang tidak kecil.
Ketika memasuki dunia kampus, status anak tunggal kembali diuji. Ruang akademik dan organisasi menuntut kerja kolektif, kemampuan berkompromi, dan kecakapan membaca dinamika sosial. Bagi anak tunggal, ini bukan hal yang asing, tetapi sering kali melelahkan. Kami harus menyesuaikan diri dari pola individual ke pola komunal. Tidak jarang, sikap mandiri disalahartikan sebagai tidak mau bergantung, atau kebiasaan reflektif dianggap sebagai sikap tertutup.
Namun, menjadi anak tunggal juga melatih kepekaan yang jarang disadari. Karena terbiasa berinteraksi dengan orang dewasa sejak kecil, banyak anak tunggal memiliki kemampuan mendengar yang baik. Kami cenderung memperhatikan sebelum berbicara, menimbang sebelum bereaksi. Dalam diskusi kampus, sikap ini sering muncul sebagai kehati-hatian berpendapat dan kesadaran untuk tidak mendominasi. Bukan karena kurang percaya diri, melainkan karena terbiasa memahami batas.
Sayangnya, masyarakat masih gemar menyederhanakan identitas anak tunggal. Ketika anak tunggal memilih jalan sendiri, ia dianggap egois. Ketika ia tidak banyak bicara, ia dicap antisosial. Padahal, dalam konteks sosial hari ini—yang penuh tekanan, kompetisi, dan tuntutan performatif—kemampuan berdiri sendiri justru menjadi modal penting. Dunia tidak lagi memberi banyak ruang untuk bergantung sepenuhnya pada orang lain.
Sebagai mahasiswa, saya melihat bahwa stigma terhadap anak tunggal sering lahir dari ketidaksiapan masyarakat menerima keragaman pengalaman tumbuh. Struktur keluarga tidak lagi seragam. Ada keluarga dengan banyak anak, ada yang memilih satu, dan ada pula yang tidak memiliki pilihan. Dalam kondisi ini, memaksakan satu standar kepribadian justru mempersempit cara kita memahami manusia.
Menjadi anak tunggal bukan berarti anti-sosial, dan memiliki banyak saudara tidak otomatis menjadikan seseorang empatik. Kepribadian dibentuk oleh banyak faktor: lingkungan, pendidikan, relasi sosial, dan pengalaman hidup. Status anak tunggal hanyalah satu variabel kecil dalam perjalanan panjang tersebut.
Pada akhirnya, anak tunggal hanyalah manusia yang tumbuh dengan caranya sendiri. Kami belajar mencintai sunyi tanpa menolak kebersamaan, belajar mandiri tanpa menutup diri, dan belajar kuat tanpa selalu terlihat. Mungkin yang dibutuhkan bukan lagi pertanyaan tentang “seperti apa anak tunggal itu”, melainkan kesediaan untuk mendengar cerita mereka tanpa prasangka.
Karena setiap anak—tunggal atau tidak—berhak dipahami sebagai manusia utuh, bukan sekadar hasil dari struktur keluarga.

 1 week ago
10
1 week ago
10