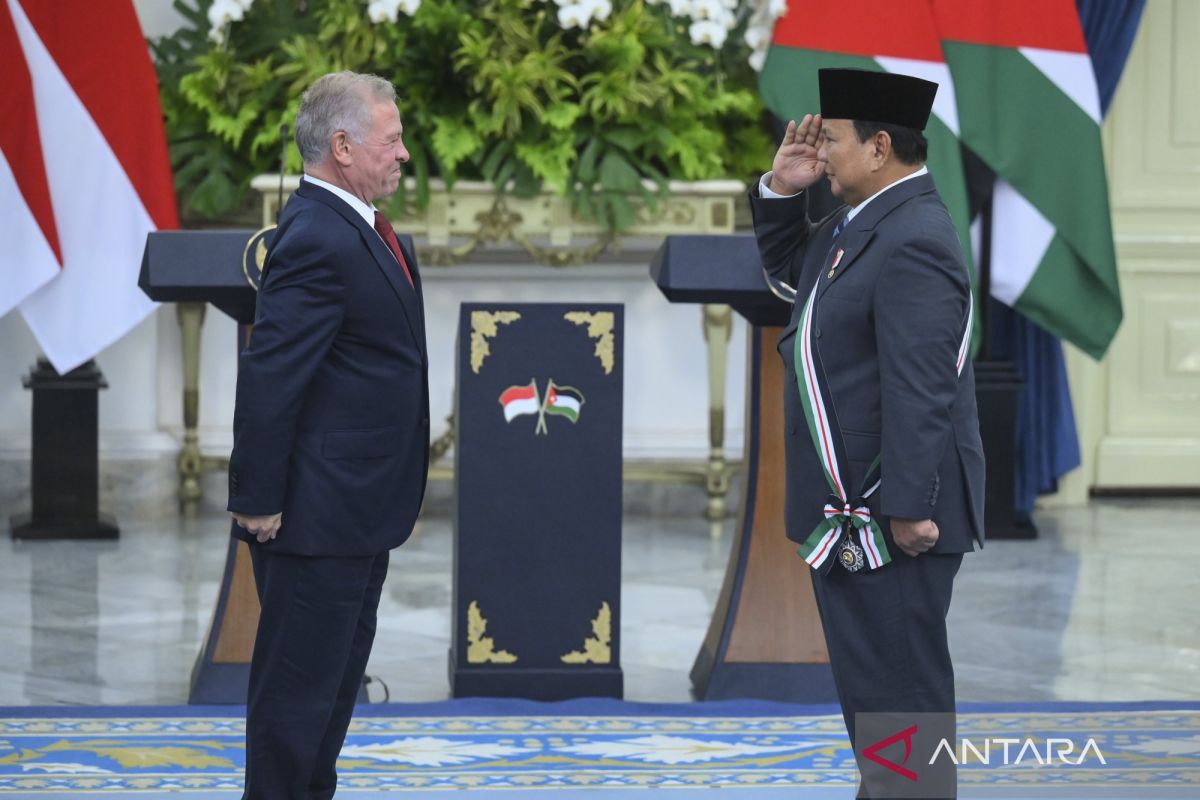Sepanjang tahun 2025 lalu, ruang publik diwarnai ekspresi kekecewaan seperti tagar #KaburAjaDulu, “Indonesia Gelap”, dan #PeringatanDarurat yang merefleksikan keresahan generasi muda terhadap kondisi sosial dan ekonomi dalam negeri. Memasuki 2026, Indonesia sebenarnya berada pada fase penting dengan sejumlah agenda pembangunan baru, mulai dari penguatan ekonomi produktif, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan kesejahteraan yang lebih merata.
Di titik inilah refleksi atas 2025 menjadi relevan. Bukan untuk mempertahankan pesimisme, melainkan untuk membaca ulang berbagai kegelisahan yang muncul sebagai bahan evaluasi kebijakan ke depan. Tahun yang baru semestinya menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali kepercayaan dan keterlibatan generasi muda, mengingat kemajuan bangsa tidak lahir dari ketiadaan masalah, melainkan dari kemampuan merespons persoalan secara nyata.
Ekspresi Kegelisahan Generasi Muda di Ruang Digital
Sejumlah ekspresi kegelisahan yang paling menonjol datang dari ruang digital. Tagar #KaburAjaDulu, “Indonesia Gelap”, dan #PeringatanDarurat mencuat di media sosial sebagai ekspresi kegelisahan generasi muda terhadap kondisi sosial-ekonomi di Indonesia. Melalui tagar ini, warganet saling berbagi dorongan untuk bekerja, studi, hingga membuka usaha di luar negeri. Fenomena ini tidak berdiri sebagai tren sesaat, melainkan berkembang sebagai kritik terhadap kesenjangan yang masih dirasakan, terutama dalam akses pendidikan, lapangan kerja, dan kesejahteraan.
Keresahan tersebut berangkat dari pengalaman yang konkret: peluang kerja yang dinilai semakin sempit, upah yang tertinggal dari kenaikan biaya hidup, serta persepsi terbatasnya ruang inovasi dan keadilan ekonomi. Dalam konteks ini, meluasnya penggunaan tagar menjadi dapat dipahami. Hingga 2025, #KaburAjaDulu tercatat telah digunakan dalam lebih dari 173.900 unggahan di TikTok (Unesa, 2025).
Temuan ini diperkuat oleh data survei terhadap responden usia 18–35 tahun menunjukkan bahwa 82% menyebut pendapatan yang lebih tinggi sebagai alasan utama keinginan pergi ke luar negeri (Populix, 2025). Pada saat yang sama, tingkat pengangguran usia muda 15–24 tahun melampaui 16%, dengan lebih dari 7 juta penganggur nasional, termasuk lebih dari satu juta lulusan perguruan tinggi.
Padahal, UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian secara tegas menempatkan penciptaan dan perluasan kesempatan kerja sebagai salah satu tujuan pembangunan industri nasional. Namun, dalam praktik, orientasi kebijakan industri kerap lebih menitikberatkan pada efisiensi produksi dan realisasi investasi berskala besar, tanpa diimbangi strategi yang konsisten untuk penyerapan tenaga kerja, khususnya bagi generasi muda. Akibatnya, pertumbuhan industri tidak selalu berbanding lurus dengan penciptaan pekerjaan yang nyata dan berkelanjutan.
Dari sudut pandang hukum, lemahnya penyerapan tenaga kerja muda bukan sekadar soal kebijakan yang tidak berjalan di lapangan. UU Cipta Kerja sejak awal dirancang untuk mempermudah investasi dan kegiatan usaha, tetapi tidak secara tegas mewajibkan agar kemudahan tersebut benar-benar diikuti dengan penciptaan lapangan kerja. Di sinilah terlihat politik hukum yang diambil negara, yakni mendorong efisiensi dan kepastian bagi investor, dengan risiko mengesampingkan tujuan keadilan sosial berupa akses kerja yang luas. Akibatnya, ketika lapangan kerja tidak tumbuh seiring masuknya investasi, kondisi tersebut bukanlah penyimpangan, melainkan hasil yang dapat diperkirakan dari arah kebijakan yang dipilih.
Dengan demikian, sederet narasi kekecewaan yang mewarnai tahun 2025 tidak dapat dipahami sekadar sebagai wacana digital, melainkan sebagai indikator adanya jarak antara aspirasi generasi muda dan realitas struktural yang mereka hadapi hari ini. Jarak ini, pada gilirannya, tidak dapat dilepaskan dari persoalan ketimpangan yang lebih luas.
Ketimpangan Wilayah dan Konsentrasi Peluang
Data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih berlangsung secara timpang antarwilayah. Per Maret 2024, Rasio Gini nasional berada di angka 0,379, dengan ketimpangan yang lebih tajam di wilayah perkotaan (0,399) dibanding perdesaan (0,306). Jakarta bahkan mencatat Rasio Gini sebesar 0,441, mencerminkan konsentrasi pendapatan yang tinggi di pusat ekonomi nasional tanpa diikuti pemerataan kesejahteraan (BPS, 2024).
Ketimpangan tersebut tercermin jelas dalam perbedaan upah antarwilayah. Di sektor pertanian, upah di Yogyakarta sekitar Rp771 ribu per bulan, sementara Jakarta mencapai Rp3,18 juta. Di sektor industri, upah di NTT sekitar Rp926 ribu, berbanding Rp4,44 juta di Jakarta. Di sektor jasa...

 2 days ago
5
2 days ago
5