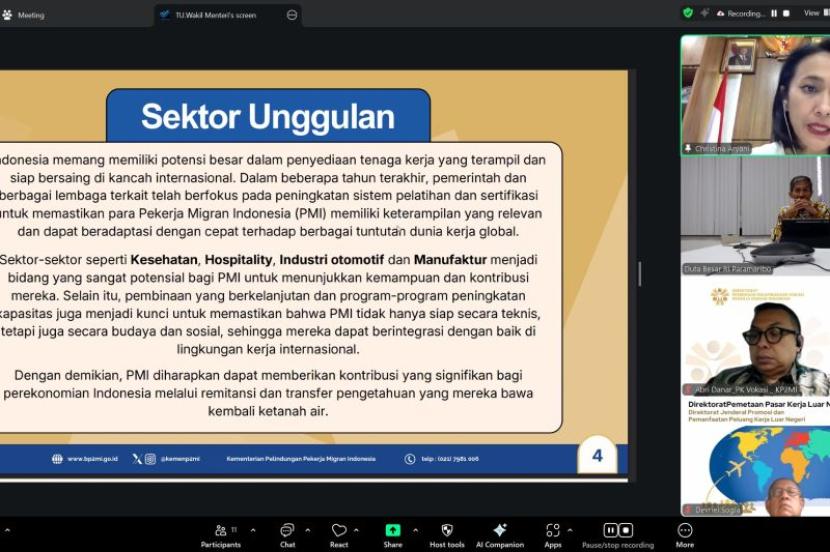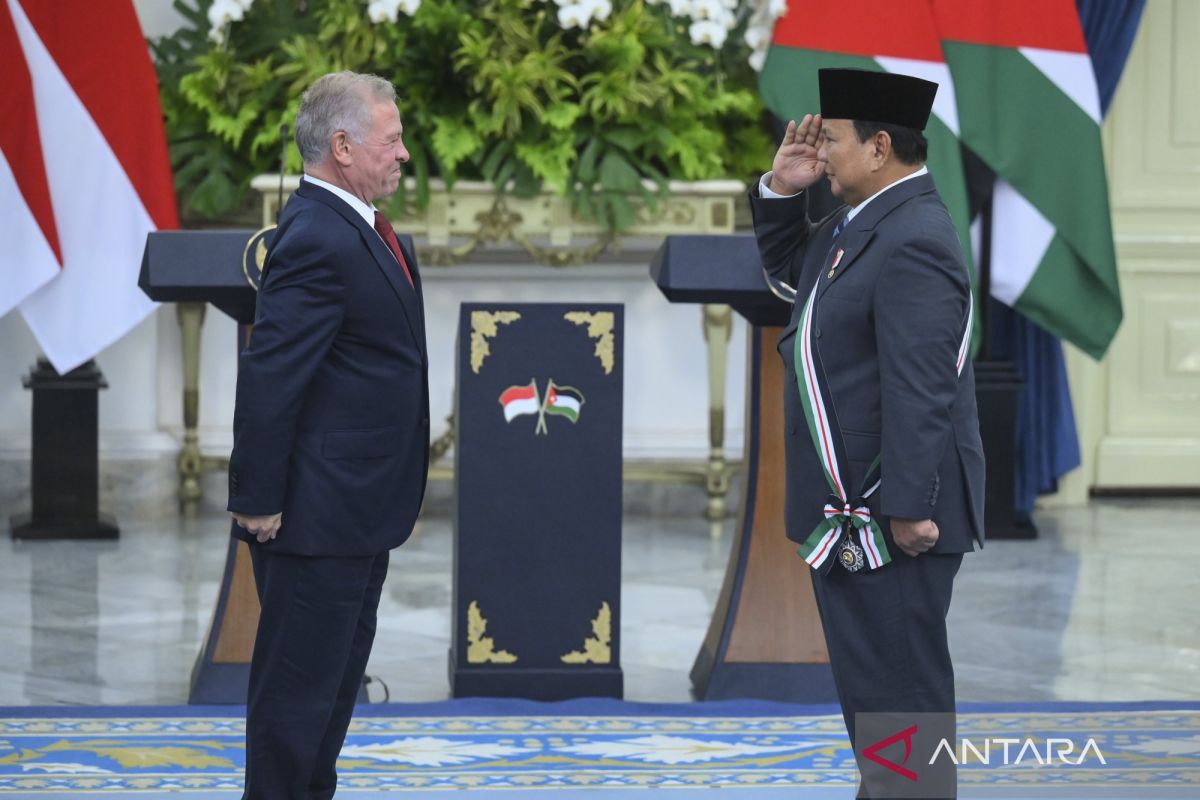Kasus-kasus yang merugikan konsumen terus berulang, tetapi revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) tak kunjung menemui kepastian. Dalam beberapa tahun terakhir, konsumen Indonesia dihadapkan pada kenyataan pahit.
Data pribadi mereka bocor, disalahgunakan, dan diperdagangkan, sementara mekanisme perlindungan hukum berjalan tertatih. Ironisnya, di tengah eskalasi pelanggaran tersebut, negara justru tampak ragu dan lamban menuntaskan revisi UUPK.
Padahal, wacana terkait revisi UUPK menjadi salah satu Prolegnas Prioritas 2025 yang seharusnya sudah diproses DPR RI. Namun, sampai sekarang tak kunjung terealisasi juga.
Situasi ini tentunya menimbulkan pertanyaan: Mengapa revisi UUPK terus tertunda, padahal kerugian konsumen semakin nyata dan sistemik, khususnya dalam relasi konsumsi berbasis data?
UUPK dalam Bayang-Bayang Zaman
Dalam beberapa tahun terakhir, publik berulang kali dikejutkan oleh kebocoran data pelanggan layanan digital, pengguna platform perdagangan elektronik, nasabah layanan keuangan, hingga peserta layanan publik.
Polanya nyaris seragam: data pribadi konsumen tersebar, dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab, dan berujung pada penipuan, teror pemasaran, bahkan kerugian finansial. Namun, ketika konsumen menuntut pertanggungjawaban, proses hukum sering kali berakhir buntu.
Konsumen kerap tidak mengetahui siapa yang harus dimintai tanggung jawab: apakah pengelola platform, mitra usaha, atau pihak ketiga. Mekanisme ganti rugi tidak jelas, sementara beban pembuktian justru diletakkan pada konsumen. Dalam banyak kasus, pelaku usaha berlindung di balik klausul baku dan dalih kepatuhan prosedural.
Fenomena ini menunjukkan satu hal; kerangka perlindungan konsumen yang ada tidak lagi memadai untuk menghadapi ekonomi digital yang berbasis data.
UUPK disusun dalam konteks ekonomi konvensional, ketika relasi konsumsi masih didominasi transaksi langsung dan produk berwujud. Konsep pelaku usaha, kerugian konsumen, dan tanggung jawab hukum dirumuskan dalam logika abad ke-20. Akibatnya, ketika data pribadi menjadi “mata uang baru” dalam transaksi digital, UUPK kehilangan daya jangkaunya.
Dalam praktik ekonomi digital, konsumen sering kali dipaksa menyetujui kontrak baku elektronik yang panjang dan tidak transparan. Persetujuan atas penggunaan data pribadi menjadi formalitas semu.
Ketika data tersebut bocor atau disalahgunakan, konsumen tidak hanya kehilangan privasi, tetapi juga mengalami kerugian nyata. Namun, UUPK belum secara tegas menempatkan pelindungan data pribadi sebagai bagian integral dari hak konsumen. Di sinilah urgensi revisi UUPK seharusnya menjadi tak terbantahkan.
UU PDP, Revisi UUPK, dan Negara
Pengesahan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sering dijadikan alasan implisit untuk menunda revisi UUPK. Seolah-olah kehadiran UU PDP telah cukup menjawab seluruh persoalan. Pandangan ini keliru dan berbahaya.

 2 days ago
5
2 days ago
5